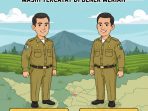Oleh : Nanda Winar Sagita*
Sebenarnya saya tidak ingin memulai tulisan ini dengan pernyataan paling klise tentang sejarah, tapi sialnya saya harus memulainya dari sana: sejarah selalu ditulis oleh pemenang.
Ya, itu sudah menjadi semacam ungkapan paling sering didengar soal permasalahan sejarah yang itu-itu melulu. Katakanlah misalnya pada Perang Dunia II yang menang adalah Blok Timur yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang; tentu sejarah yang kita kenal akan sangat berbeda jadinya.
Tidak ada kisah Holocaust yang selalu dibesar-besarkan, dan tidak ada pula konflik antara Israel dan Palestina karena sudah pasti Inggris tak punya kuasa untuk memindahkan orang-orang Yahudi di Eropa ke wilayah Timur Tengah.
Itu soal lain, tapi masalah yang sedang gencar-gencarnya adalah Menteri Kebudayaan berencana untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Sekarang kita perlu bertanya: memangnya apa yang salah dari sejarah versi pemerintah sebelumnya?
Mengutip pernyataan teman saya Angga Prasetya, seorang guru sejarah di Rusip, dia yakin sejarah hanya sebatas omong kosong yang terus diulang-ulang. Itu benar, sekaligus tidak benar.
Benar karena sejarah selalu tidak bisa melepaskan diri dari bias penulisnya. Katakanlah misalnya pada masa kami sekolah dulu, materi sejarah yang diajarkan fokus pada Jawasentrisme, yang mana peran daerah-daerah lain jelas terkucilkan.
Itu terjadi karena penulisnya adalah para sejarawan dari Jawa dan kurikulum yang disatukan juga mengharuskan anak-anak SMA di Gayo sampai Papua pun lebih kenal pada Pangeran Diponegoro ketimbang Aman Nyerang atau Frans Kaisiepo, misalnya. Dengan demikian, sejarah tidak lebih dari omong kosong yang terus diulang-ulang.
Di sisi lain, pernyataan itu tidak benar karena sejarah selalu punya metodologis ilmiah untuk menulisnya. Orang tak bisa sembarangan bilang Buntul Linge dulunya sebuah pulau yang dikelilingi lautan dan mengeklaimnya sebagai kebenaran, sementara pada saat yang sama orang di seluruh dunia juga punya versi sejarah lain dan menganggap itu hanya lelucon.
Tentu saja sumber lisan dan tulisan sama kuatnya untuk dijadikan sebagai sumber sejarah, masalahnya hanya ada pada bagaimana penulis meramunya agar terdengar masuk akal.
Nah, dengan menulis ulang sejarah kita seolah-olah dituntun untuk mempercayai satu sejarah versi Pemerintah dan mengabaikan sejarah versi lain yang sifatnya lebih marjinal.
Padahal bisa jadi objektivitas sejarah versi marjinal jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang yang versi Pemerintah.
Tidak mungkin sejarah versi pemerintah tak punya kepentingan di baliknya. Misalnya baru-baru ini beredar informasi bahwa Presiden Soeharto akan diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
Dalam versi Pemerintah, hal itu lumrah saja mengingat statusnya yang sudah terlanjur dianggap sebagai Bapak Pembangunan; dan juga mengingat hubungan pribadi Presiden Prabowo dengan Presiden Soeharto.
Tapi di balik itu, ada sejarah versi lain yang harus kita pertimbangkan. Misalnya Soeharto telah melakukan genosida terhadap orang-orang yang dituduh PKI (seperti kata Bang Mustawalad, ada yang benar-benar PKI ada yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjadi korban “tilok wan opoh kerong”).
Bukan hanya itu, di sepanjang pemerintahannya, ada pula masalah penculikan aktivis, kasus Petrus yang memberangus para preman, dan juga pembungkaman media yang terlalu kritis pada Pemerintah.
Dengan alasan demi menjaga keutuhan negara atau mempertahankan nilai-nilai Pancasila, semua itu jelas menciderai kemanusiaan.
Apapun alasannya, hak hidup dan kebebasan berpendapat jauh lebih penting ketimbang mempertahankan kuasa rezim yang tidak akan selamanya bertahan di tampuk kekuasaan.
Melihat hal itu, kita perlu mempertanyakan: seberapa penting sih sejarah Indonesia itu ditulis ulang. Kalau harus memilih satu jawaban, ya barangkali tidak bisa karena kita akan selalu terjebak dalam dilema.
Sejarah selalu akan berubah seiring dengan penemuan sumber-sumber baru. Tapi yang pasti untuk menulis ulang sejarah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.
Adapun beberapa hal yang saya maksud adalah kepentingan di baliknya yang sudah tentu bakalan ada unsur propaganda untuk membesarkan status Pemerintah yang sedang berkuasa.
Tak pelak lagi, dengan demikian sejarah tetap hanya sebatas alat untuk mengendalikan jalan pikiran masyarakat; sementara setiap orang punya hak untuk menentukan mana yang layak dipercaya dan mana yang hanya sebatas omong kosong belaka.
Saya sendiri adalah seorang guru sejarah. Dengan demikian saya punya kuasa besar untuk memilih sejarah mana yang akan saya ajarkan kepada siswa saya dan mana yang tidak.
Dengan begitu, segencar apa pun Pemerintah berusaha menulis ulang sejarah, saya punya hak untuk mengajarkan atau tidak mengajarkan versi sejarah itu kepada para siswa saya.
Hal itu karena saya yakin betul: buku sejarah mungkin bakal ditulis oleh pemenang, tapi kami akan memilih bacaan yang lain.