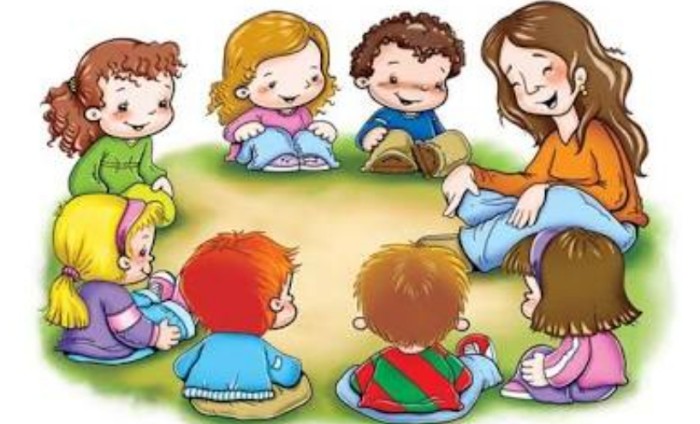Oleh : Dr. Joni, MN Aman Rima*
Merupakan bentuk sastra lisan suku Gayo yang berbentuk cerita, cerita dalam bentuk ure-ure ini hampir sama seperti “kekeberen”.
Perbedaan antara “ure-ure” dan “kekeberen” adalah terletak pada akhir cerita dan durasi bercerita dan panjangnya cerita yang digunakan.
“Kekeberen” umumnya bentuknya cerita yang dilakukan secara monolog, yang lain hanya mendengar, selanjutnya pesan yang terdapat di dalam cerita tersebut dimaknai oleh masing-masing pendengar, biasanya dilakukan oleh nenek dengan cucunya di saat sambil tidur atau cerita sambil tiduran. Tetapi tidak jarang juga dilakukan oleh kakek-kakek dan sesama anak muda, genrenya beragam ada lucu, ada sedih, ada perjuangan, ada kisah, ada sejarah dan lain-lainnya.
Kekeberen ini sering hadir dari seseorang ketika saat waktu santai atau tidak dalam kondisi sibuk dengan pekerjaan rumah, di kebun, di sawah dan pekerjaan lainnya.
Ure-Ure dalam sastra Gayo jalan ceritanya hampir menyamai bentuk “Kekeberen”, tetapi dalam “Ure-Ure” selalu diakhiri dengan pertanyaan, umumnya pertanyaannya lebih mengarah kepada teknis dan strategi bagaimana dalam menghadapi dan menyikapi problem dalam hidup.
Berikut contoh bentuk “Ure-Ure” yang ada di suku Gayo, sebagai berikut:
… I wan sara lo, lo ne porak pedeh, ko beluh ku uten mungenal utem, tikik mi male sawah ku ton si tuju ko, ko teduh karena porak pedeh, I waktu oya ko olok pedeh gerahen, gere mah wih pe ko ari umah.
Sawah I sara ton, ara engon ko sara batang ni asam, uwah ni asam ne pe gere dele, cumen I atas cabang ni batang si muwah ne ara engkong betapa, ….. “kune cara mu munuwet uwah ni asam a ne kin uak ni gerahen?”, ko nge sawah gerahen ne, oyawe sara batang ni asam wan uten oyane…
Ditilik berdasarkan Ure-Ure di atas dapat dimaknai bahwa isi ceritanya adalah ‘ada salah seorang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, cuaca saat itu sangat panas, orang tersebut pergi ke hutan berjalan kaki, tiba suatu tempat yang hampir sampai ke tempat yang ia tuju, ia berhenti dan ia melihat sebuah pohon jeruk dan buah pohon jeruk itu pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa cabang saja yang berbuah, namun di dahan yang berbuah itu ada seekor monyet besar, bulunya pun sudah memerah, jenis monyet ini sangat berbahaya jika diusik atau diganggu.
Orang tersebut sudah sangat haus, sementara ia tidak membawa bekal air, ia hanya mengharap buah jeruk itu untuk menghilangkan hausnya. Yang menjadi pertanyaan, “Bagaimana orang ini bisa mendapatkan buah jeruk tersebut untuk mengobati hausnya?”, sementara monyet besar tersebut tidak mau pergi dari dahan jeruk yang berbuah tersebut.
Dalam konteks Ure-Ure ini dapat ditarik kesimpulannya, bahwa bentuk sastra lisan dalam modus ure-ure ini lebih kepada mengasah pikiran seseorang lebih kritis dan melatih untuk cepat dan tangkap mengeluarkan ide, jika dalam dunia pendidikan dan politik hal ini dapat disebut dengan strategi dalam mendapatkan sesuatu tetapi tanpa mengusik dan menganggu kedudukan orang lain.
Istilahnya “lipe“boh mate ranting gere mupolok” artinya ‘usahakan ular itu bisa mati tetapi usahakan ranting yang digunakan untuk memukul ular tersebut tidak patah.
Maksudnya, apa yang diinginkan dapat tercapai tetapi dengan tidak merusak dan menyakiti orang lain.
Dalam konteks ini juga demikian, bagaimana buah jeruk tersebut dapat diambil oleh orang tersebut untuk mengobati hausnya, tetapi bagaimana cara monyet besar tersebut tidak merasa ia diganggu, agar semuanya aman-aman saja.
Dalam konteks inilah si pendengar cerita ure-ure tersebut harus benar-benar mengerti dan paham
Inilah bentuk sastra lisan yang terdapat di Gayo dan yang dimiliki oleh suku Gayo, jika digolongkan ke dalam sastrra, Ure-Ure ini masuk kedalam bentuk ‘Seloka’. Jadi, bentuk seloka dalam bentuk ure-ure ini adalah bermodus berpikir kritis dan mendidik.
Jadi, ure-ure dalam hal ini adalah bentuk sastra lisan yang bersifat mendidik dan strategi menemukan mencari solusi ketika kita menemukan suatu problem hidup.
Dalam hal ini telah jelas bahwa suku Gayo pada hakekatnya memiliki kekayaan budaya yang tak benda yang dapat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menempuh praktik berkehidupan bersama.
*Penulis adalah ketua bidang pendidikan dan penelitian di Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah