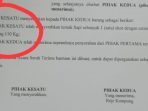Oleh : Marah Halim*
Masih ingat lirik sebuah lagu dangdut “aduh-aduh-aduh….aduh-duh, mana tahaaan!”, meski dalam konteks yang berbeda, diksi-nya sepertinya relevan menggambarkan betapa rapuhnya daya tahan masyarakat di Dataran Tinggi Gayo (Datinggo) menghadapi bencana alam.
Masih sebulan lebih yang lalu bencana banjir dan longsor menerpa Datinggo, ketika itu hanya dalam waktu beberapa hari salah seorang kepala daerah-nya menyatakan “mana tahan” dengan kondisi yang ada.
Ya, memang terbukti bahwa banyak aspek ketahanan yang sangat rentan, yang paling utama adalah tidak adanya ketahanan pangan dan ketahanan energi; dua ketahanan yang bersifat mutlak bagi masyarakat di sana.
Beras adalah simbol ketahanan pangan bagi masyarakat Datinggo. Jika beras sudah aman, maka amanlah semua aman (kepala keluarga) yang ada disana. Ada beras ada makan, tapi kalau beras tidak ada, walaupun sudah makan singkong satu panci belumlah dianggap makan.
Beras adalah harga diri setiap keluarga. Dalam keadaan normal, tidak ada beras di rumah -apalagi ketika ada tamu- adalah aib.
Sebetulnya saat bencana banjir dan longsor datang, jika beras tersedia dalam stock yang aman, baik di setiap keluarga atau di Bulog, keadaan tidak akan terlalu mencekam. Tapi budaya menyimpan padi untuk beras untuk jangka panjang sama sekali sudah hilang dari budaya masyarakat Gayo.
30 tahun yang lalu, masih ada keluarga yang menyimpan padi-nya di keben (lumbung padi) yang cukup besar untuk menyimpan padi untuk satu musim tanam sebelum panen berikutnya, tapi keben kini tinggal kenangan.
Seiring dengan tergerusnya lahan pertanian menjadi “hutan bata dan baja”, keberadaan keben tak dianggap penting lagi. Banyak bangunan keben yang diruntuhkan dan materialnya seperti papan, tiangnya dialihkan untuk bangunan lain; terutama karena material kayu untuk keben biasanya dipakai material kayu yang paling bagus; kuat, anti rayap dan tidak mudah buruk.
Saat ini kebutuhan beras untuk masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues betul-betul bergantung pada beras dari wilayah pesisir seperti terutama kabupaten terdekat, yakni Bireuen dan Aceh Utara.
Kalaupun masih ada sawah namun hasilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestiknya; pun lagi musim tanamnya yang hanya sekali setahun dengan umur padi 6 bulan.
“Mana tahan” yang kedua adalah ketahanan energi. Tanpa transportasi tidak mungkin setiap kepala keluarga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti beras, BBM adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat.
Tapi transportasi di dataran tinggi mengandalkan alat transportasi bermesin, dan mesin sejauh ini tidak bisa digerakkan dengan air, mutlak dengan bahan bakar fosil. Ketika pasokan BBM macet, maka otomatis gezah kehidupan di Datinggo menjadi mati suri. Tanpa bensin, tanpa listrik, peradaban kembali ke zaman behaula.
Ke depan, pemerintah daerah di ketiga kabupaten perlulah mempertimbangkan membangun lumbung pangan dan lumbung energi di setiap kecamatan, sehingga dalam kondisi post majeure seperti bencana alam saat ini masyarakat bisa bertahan minimal untuk beberapa minggu sebelum mereka dapat beradaptasi dengan keadaan.
Dua ketahanan ini, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi, atau ditambah lagi dengan ketahanan listrik; perlu dipikirkan secara mendalam dan dicadangkan solusi yang paling efektif dan efisien. Untuk listrik, sudah masanya memanfaatkan panas bumi Burni Telong sebagai sumber energi listrik di Datinggo.
Mungkin jajaran Pemda di tiga kabupaten perlu perlu benchmarking ke Islandia, negara kecil di Skandinavia yang listriknya sepenuhnya bersumber dari panas bumi.
Mungkin karena panas bumi Burni Telong tidak pernah dimanfaatkan membuat “tenggorokannya” tertekan sehingga memicu “batuk kecil” yang membuat warga Bener Meriah eksodus dan tidak bisa tidur nyenyak. []