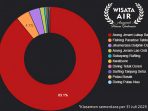Oleh : Fauzan Azima*
PADA 1976, di Hotel Indonesia, Jakarta, menjelang deklarasi Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Muhammad Hasan di Tiro bertemu dengan Tengku Ilyas Leube. Keduanya membahas strategi memerdekakan Aceh.
Dalam pertemuan itu, deklarator Aceh Merdeka, Tengku Hasan Tiro, menawarkan jabatan kepada Tengku Ilyas Leube. Tapi tawaran itu tidak langsung dijawab oleh koleganya. Terutama dengan mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk sejarah dan prediksi Aceh di masa depan.
“Demi Aceh tanah mulia, izinkan Tengku mengangkat saya sebagai Menteri Keadilan,” kata Tengku Ilyas Leube. Jawaban itu belum terpikirkan oleh Tengku Hasan Tiro.
Bagi Tengku Ilyas Leube, ketidakadilan membekas dalam ingatannya. Ketika dia masih menjadi santri di Dayah Pulo Ketun, Bireueun, pada 1930-an, sempat terjadi perkelahian antarsantri yang melibatkan santri dari Gayo.
Teungku Ali Husni atau terkenal dengan sebutan Tengku Kali Tama, asal Kala Kebayakan, merasa dizalimi. Dia melawan seorang diri. Tapi yang akhirnya 100 orang lebih santri asal Gayo terusir dari dayah yang sangat populer pada waktu itu.
Nasib orang Gayo dalam perkembangan selanjutnya tidak mendapat porsi yang adil di pemerintahan. Sampai saat ini, misalnya, aparatur sipil negara asal Gayo kerap merasa skeptis untuk mengikuti tes sebagai kepala dinas karena peluang mereka untuk masuk ke jajaran tiga besar tipis.
Adapun Nova Iriansyah, yang bisa menjabat sebagai Gubernur Aceh, sering direndahkan. Dia dianggap sebagai kecelaan dan kecelakaan sejarah. Selama menjabat, siang malam di-bully. Benar pun yang dikerjakan Nova Iriansyah dianggap salah, konon lagi yang salah.
Begitupun dalam porsi anggaran untuk wilayah Gayo. Di tengah gelimang dana dari pusat yang diterima Aceh, porsi untuk Gayo tergolong minim. Lantas munculkan ide dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengubah skema pembagian Dana Otonomi Khusus Aceh.
Dalam sebuah kesepakatan, TAPA dan Banggar mengubah porsi DOKA dari 60 persen pengelolaan di tingkat provinsi, membengkak menjadi 80 persen. Ini artinya, seluruh daerah di Aceh, semakin kecil.
Wajar jika suara penolakan terhadap rencana itu disuarakan oleh banyak kalangan di banyak daerah. Kebijakan ini dinilai merusak perekonomian Aceh secara keseluruhan. Inilah praktik nyata ketidakadilan provinsi terhadap kabupaten dan kota.
Kita pernah memberontak karena ketidakadilan Jakarta terhadap Aceh. Setelah damai sepatutnya kita membangun kepercayaan bersama dengan menjadikan pemerintah provinsi sebagai simbol pemersatu bagi semua daerah, terutama untuk wilayah tengah, tenggara, dan barat-selatan.
Tapi kini, atas nama “uang pokir”, ketidakadilan itu dilembagakan. Bahkan oleh lembaga yang seharusnya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kapalo.
(Mendale, November 23, 2023)