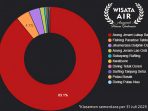Oleh : Win Wan Nur*
Menjelang habisnya masa jabatan bupati, seperti biasa terjadi di negara demokrasi manapun, suasana politik di Gayo mulai menghangat. Beberapa nama kandidat bupati mulai diapungkan, beberapa survey, mulai dari yang serius sampai sekelas survey di facebook dan warung kopi mulai muncul ke permukaan.
Ini adalah suasana khas di negara-negara yang menganut paham demokrasi, untuk itu di sini saya mencoba mengulas fenomena ini, fenomena demokrasi modern.
Demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang (bukan demokrasi awal di masa Yunani kuno) muncul pada masa pencerahan di Eropa.
Demokrasi seperti yang sekarang, muncul pasca hancurnya kekuasaan Gereja yang memonopoli kebenaran berdasarkan doktrin yang dikuasai oleh sekelompok orang.
Gerakan pencerahan membuat persepsi atas kebenaran tidak lagi bergantung pada doktrin, melainkan pada pengamatan panca indera, yang bisa dipersepsi secara sama oleh semua manusia dalam bentuk kongkrit.
Dalam suasana seperti inilah demokrasi sebagaimana yang kita kenal sekarang berkembang, sebagai antitesis dari sistem feodal.
Kalau dalam sistem feodal, rakyat hanya bertindak fasif ‘sami’na wata’na’ yang ikut saja apa kata raja, di mana pemimpin dipandang sebagai satu sosok istimewa yang mampu bersikap adil dan bijaksana dan terpelihara dari segala bentuk kesalahan manusiawi dan kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang mulia.
Demokrasi sebaliknya, dalam sistem ini masyarakat justru berperan sangat aktif dalam mengontrol pemerintahan.
Perbedaan mencolok antara sistem feodal dan demokrasi terlihat bagaimana kedua sistem ini memandang kekuasaan.
Sistem feodal memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang mulia anugerah dari langit, karena itulah dalam sistem feodal, penguasa biasanya mengklaim diri sebagai sosok yang lebih istimewa dari rakyat kebanyakan, entah itu keturunannya, atau benda yang dimilikinya. Kalau di Gayo, misalnya dulu raja mengaku keturunan dari kekuasaan Islam terbesar saat itu, Turki, alias Negeri Rum. Sehingga, itu membuatnya berhak diperlakukan istimewa dan dipatuhi rakyat biasa. Meski kenyataannya, ini tak begitu sukses diterapkan di Gayo yang egaliter, tapi preseden seperti itu ada.
Sebaliknya, dalam sistem demokrasi kekuasaan justru dipandang cenderung korup, di mana kekuasaan absolut dilihat sebagai korup absolut.
Dalam sistem demokrasi, setiap pemimpin yang terpilih melalui sistem demokratis diyakini memiliki potensi besar untuk korup dan menyeleweng, karena itulah segala tindak tanduknya harus diawasi dengan ketat.
Itulah yang membuat adanya pembagian kekuasaan, Trias Politika dan adanya pilar demokrasi keempat yaitu media, yang di zaman internet ini mulai bergeser sedikit menjadi netizen penguasa media sosial yang jauh lebih cair ketimbang media-media klasik di masa lalu.
Dalam satu masyarakat demokratis yang ideal, ketika seorang kandidat pemegang kekuasaan publik berkampanye menyampaikan visi misinya. Mereka akan melengkapinya dengan penjelasan kongkrit dan masuk akal, lengkap dengan uraian detail tentang bagaimana dia akan melaksanakan visi dan misinya.
Ini harus dia lakukan, karena dalam iklim demokrasi yang ideal ini, masyarakat tidak pernah memandangnya sebagai sosok pilihan dari langit, melainkan hanya sosok manusia biasa yang tak jauh berbeda dengan pemilihnya. Logis atau tidaknya penjelasannya inilah yang akan dinilai oleh masyarakat pemilih ketika mereka akan menentukan pilihan di dalam bilik suara.
Benar atau salahnya sebuah pendapat, visi misi dan kebijakan yang disampaikan dalam kampanye, semuanya diukur dalam batasan kongkrit.
Contoh : ketika seorang calon pimpinan pemerintahan dalam visi misinya mengatakan dia akan “Mengundang kemakmuran dan menghalau kemiskinan, akan memberikan tanah 2 hektar per kepala keluarga, dan seterusnya.”
Masyarakat di negara demokratis yang benar tidak akan terpukau dengan kata-kata indahnya. Tapi mereka akan melihat, kata-kata yang disampaikan itu, bernilai atau tidak.
Bernilai atau tidaknya jargon itu, dilihat dari logis atau tidaknya detail pemaparan strategi untuk mencapainya.
Semua itupun, dinilai tentu saja berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif.
Artinya, ada penjelasan apa yang disebut miskin, lengkap dengan ukuran kuantitatif, misalkan rumahnya beralas tanah, penghasilannya kurang dari sekian juta dengan tanggungan sekian anak, dan sebagainya.
Setelah jelas definisi miskinnya, lalu diuraikan, berapa jumlahnya.
Setelah itu baru dibahas, bagaimana cara menghalaunya, paket kebijakan apa yang akan disiapkan untuk mencapainya. Dari sanalah masyarakat pemilih menilai kualitas dari sebuah Jargon politik. Dan ketika sang calon sudah terpilihpun, angka-angka itu akan menjelaskan berhasil atau gagalnya si calon setelah dia benar-benar memimpin.
Itu cerita di negara yang berdemokrasi dengan benar. Logika dan fakta kongrit dijadikan sebagai ukuran dalam menilai.
Kritik terhadap kebijakan itu juga ada nilainya, bukan asal sembur. Kritik di negara yang berdemokrasi dengan benar juga kongkrit, terkait pencapaian, terkait dengan kebijakan dan seterusnya.
Di negara demokratis seperti ini meritokrasi (suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan) menjadi sebuah keniscayaan. Untuk bisa sukses pemerintah di negeri seperti ini mau tidak mau terpaksa harus adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pimpinan sebuah dinas atau departemen, dan mau tidak mau terpaksa meminggirkan mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Meskipun mereka adalah kerabatnya mereka sendiri.
Di negara seperti itu, tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya tahu ikut kemana sang pemimpin pergi, TOPAN kalau menurut istilah populer di Takengen saat ini.
Tapi masalahnya, tidak semua negara yang menerapkan sistem demokrasi sudah melewati tahap ‘Aufklarung’ alias pencerahan. Yang masyarakatnya secara otomatis menilai keberhasilan seorang calon berdasarkan ukuran-ukuran kongkrit.
Di banyak negara yang baru berdemokrasi, termasuk Indonesia yang mana Gayo terdapat di dalamnya, tahap pencerahan ini belum terlewati. Rata-rata masyarakat kita bahkan masih gamang dalam mengukur kegagalan atau keberhasilan ssebuah pemerintahan.
Di negara dan daerah seperti ini, masyarakat masih sangat mudah dimanipulasi oleh kekuasaan.
Di dalam masyarakat seperti ini, kritik terhadap pemerintahan masih sangat mudah diputarbalikkan oleh penguasa sebagai perbuatan tidak sopan dengan pelbagai diksi yang tidak pada tempatnya, misalnya seperti tidak punya sopan santun terhadap orang yang lebih tua, beraninya menggonggong di luar pagar dan lain sebagainya.
Bahkah orang yang jelas-jelas ilmuwan ahli di bidangya, bisa direndahkan seorang penguasa dengan cara membawa isu SARA.
Demokrasi di negara seperti ini, hanya dipahami secara formal, yaitu pemilihan yang didasarkan suara terbanyak.
Demokrasi dalam masyarakat seperti ini, alih-alih menuju meritokrasi. Yang terjadi demokrasi justru menggiring masyarakat menuju budaya Nepotisme dan Plutokrasi (suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan).
Sebab masyarakat yang belum tercerahkan cenderung memilih pimpinan pemerintahan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan dan politik uang. Dalam beberapa kasus juga didasarkan atas keturunan dan wibawa bahkan dalam beberapa kasus dengan alasan klenik.
Demokrasi model beginilah yang kita saksikan sehari-hari di dua kabupaten Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Demokrasi yang tumbuh dalam iklim masyarakat seperti ini menjadi sangat unik.
Ketidak pastian dari sebuah realitas politik yang setiap menit dan detik bisa berubah. Termasuk kesulitan mengukur persepsi publik menyangkut kepastian suara dukungan bagi pasangan kandidat. Yang diakibatkan oleh banyaknya faktor dibalik landscape politik yang bisa jadi melahirkan gaya saling tarik menarik atau tolak menolak. Tidak hanya diselesaikan dengan mendatangi seorang konsultan politik yang memberikan pertimbangan dengan menggunakan hukum probabilitas (peluang/kemungkinan) dengan sejumlah pertimbangan ilmiah berdasarkan data-data hasil survey. Melainkan juga dengan meminta nasehat pada seorang dukun, tokoh spiritual atau apapun namanya tapi intinya bersifat klenik yang mengukurnya memakai pendekatan mistis.
Kandidat yang bertarung dalam tiap tahapan pemilihan baik itu eksekutif maupun legislatif, sudah menjadi rahasia umum selain menggunakan jasa konsultan politik juga terbiasa menggunakan jasa seorang dukun dalam mengukur peluangnya.
Jadi tak perlu heran, kalau menjelang Pemilu, beberapa politisi akan mulai membranding diri sebagai pewaris Reje Linge, punya akses ke Pedang Nabi Daud dan seterusnya. Inilah yang disebut mentalitas feodal, seolah dengan segala kelebihan yang dia klaim itu, dia jadi punya hak lebih untuk berkuasa.
Kalau rakyat yang lebih cerdas, dari fenomena ini saja sebenarnya sudah bisa melihat kalau sang calon maju ke pemilihan untuk menjadi penguasa, bukan untuk menjadi pengelola dana yang diamanahkan oleh undang-undang untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Hasilnya, ketika sang kandidat terpilih sebagai pemegang kekuasaan, yang kita dapatkan bukan iklim meritokrasi melainkan iklim nepotisme. Jargon-jargon begitu indah tapi kenyataan berkata lain.
Ketika ada kritik kepada pemerintah, alih-alih mereka memperbaiki diri, tapi yang terjadi mereka menggunakan kekuatan model feodal, entah itu dengan modal uang, iming-iming proyek atau mengandalkan keturunan untuk membusukkan orang yang menyampaikan kelemahan pemerintahan yang dipimpinnya.
Dan percayalah, situasi ini tidak akan pernah berubah selama masyarakat sendiri tidak berusaha keluar dari situasi seperti ini, dengan cara mulai melihat bahwa orang-orang di pemerintahan itu adalah orang-orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengelola uang negara buat diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat banyak, yang mana setiap gerak dan kebijakannya terkait pengelolaan uang itu, boleh disorot dan dikritisi. []