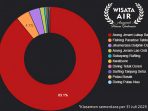Oleh : Win Wan Nur
Di hari-hari menjelang akhir tahun ini, kemacetan lalu lintas menjadi fenomena sehari-hari di Takengen, , sebuah fenomena yang tak pernah saya alami ketika saya dulu masih berdomisili di kota mungil yang tercatat sebagai tempat kelahiran saya ini.
Takengen sekarang sudah bertransformasi menjadi daerah kunjungan wisata populer bagi masyarakat pesisir Aceh dan juga dari Sumatera Utara. Kesan yang saya rasakan, Takengen ini sudah seperti Bandung bagi warga Jakarta, atau Berastagi bagi warga Medan.
Ada bermacam alasan yang membuat orang tertarik untuk mengunjungi suatu daerah untuk berwisata, dari sekian alasan tersebut, salah satu alasan yang terkuat adalah adanya perasaan “depaysement” atau “sens dépaysé” sebuah ungkapan bahasa Prancis yang tak bisa ditemukan padanannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia.
Depaysement adalah sebuah perasaan berada di tempat yang sangat berbeda, asing tapi bukan dalam konteks negatif, sebuah perasaan yang menyentuh alam bawah sadar bahwa kita sedang tidak berada di rumah tapi berada di sebuah tempat yang indah yang asing.
Inilah yang saya lihat dirasakan oleh teman-teman saya dari pesisir ketika pertama kali menginjakkan kaki di Takengen. Ketika kami berjalan kaki dari rumah saya di Dedalu ke One one, melihat, dengan landscape perbukitan dengan bebatuan yang menonjol bukit dengan sange dan uyem dan pohon Jedem yang tumbuh liar, suhu dingin dan pemandangan danau di sebelah kiri, menimbulkan suatu perasaan depaysement yang sangat kuat.
Kuatnya sensasi “depaysement” inilah yang membuat daerah-daerah wisata di dunia terus dikunjungi wisatawan.
Untuk daerah-daerah wisata populer dan stabil dikunjungi wisatawan, sensasi depaysement ini datang bukan hanya dari alamnya, tapi juga dari arstitektur bangunan yang ada di tempat itu. Ini yang kita lihat di Eropa atau Jepang. Selain alamnya, bangunan di Eropa dan Jepang membuat kita merasakan sensasi “depaysement” yang sangat kuat.
Untuk di Indonesia, sensasi depaysement yang sangat kuat saya rasakan terkait bangunan ini ada di Bali. Jangankan orang asing, kita yang orang Indonesia sendiripun akan merasakan sensasi “depaysement” ketika berada di Bali saat berada di Bali dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang ada di sana, karena gaya arsitekturnya memang tak bisa kita temukan di daerah lain di Indonesia.
Selain Bali, daerah lain yang membuat kita merasakan sensasi yang mirip meski tidak sekuat di Bali, adalah Sumatera Barat dan juga Palangka Raya. Itu karena dua daerah itu memang mempertahankan arsitektur khasnya dengan mengembangkan konsep neo vernacular, sebuah gaya arsitektur yang muncul di era Post-modern, yang menggabungkan arsitektur tradisional dan arsitektur modern. Gaya arsitektur yang membuat daerah yang mengembangkannya terlihat unik dan istimewa karena tetap mempertahankan jati dirinya.
Di Gayo, gaya bangungan neo vernacular berbasis kearifan lokal Gayo ini bisa kita lihat dalam desain pendopo bupati Aceh Tengah dan juga kantor Bupati dan DPRD dan terutama bangunan Hotel Renggali lama yang sangat ikonik.
Hotel Renggali yang lama, kalau kita lihat kembali foto-fotonya benar-benar menjadi Ikon keindahan bukan hanya Takengen, tapi tanoh Gayo secara umum. Pemilihan lokasi di Ujung Baro, dengan latar Burni Birah Panyang disempurnakan dengan arsitektur khas Gayo dengan ornament-ornamen kerawang membuat Hotel Renggali yang lama terlihat menyatu, menyempurnakan keindahan danau Lut Tawar dan bentang alam yang mengitarinya.
Secara pribadi, saya sendiri selalu membanggakan landscape hotel Renggali yang lama kepada teman-teman saya di luar daerah dan di luar negeri, karena saya sendiri memang merasakan itu adalah cerminan keindahan kultur dan warisan budaya saya yang berpadu sempurna dengan keindahan alam negeri kelahiran saya ini.
Tapi ketika saya kembali ke Takengen pada tahun 2020, alangkah kagetnya saya, Renggali yang lama sudah tidak ada lagi, berganti dengan Grand Renggali setelah diakuisi oleh PT. Grand Arabia. Celakanya, setelah diakuisisi, alih-alih mengapresiasi arsitektur berbasis budaya lokal yang menyatu dengan harmonis dengan lingkungan tempatnya berdiri, manajemen Grand Arabia mengubah tampilan wajah Hotel Renggali menjadi arsitektur bergaya jazirah Arab.
Jadi sodara-sodara, bayangkan sebuah bagunan mewah bergaya gurun pasir, dengan cat berwarna khaki yang sangat serasi dengan suasana alam gurun yang panas, kering dan dikelilingi pasir, dipaksakan berdiri di tengah bentang alam hijau, sejuk dan dikelilingi air.
Alhasil, kalau dulu, saat melihat Hotel Renggali lama, kita merasakan sensasi seperti menyaksikan mempelai perempuan yang cantik jelita dan laki-laki yang tampan mempesona duduk di kursi pengantin.
Tapi melihat tampilan eksterior Grand Renggali, kita seperti melihat seorang gadis muda cantik jelita dengan wajah sendu seperti mau menangis, duduk di pelaminan berdampingan dengan tua bangka kaya raya yang tubuhnya dipenuhi perhiasan mewah berharga mahal tapi norak. Kita yang melihatnya bukannya merasa adem, tapi emosi karena merasa seperti sedang menonton sebuah aksi pemerkosaan yang dilegalkan.
Rasa tidak nyaman itu menuntun saya untuk mencari akar penyebabnya. Saya berbicara dengan para aktivis di Gayo, dengan pejabat di Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata bahkan sampai bupati Aceh Tengah sendiri.
Kenapa “pemerkosaan legal” ini bisa terjadi?
Ternyata pangkal persoalannya adalah, regulasi pariwisata belum ada. Jangankan regulasi wisata, bahkan regulasi pendirian bangunan meski sudah ada qanunnya, terkait soal aturan arsitektur bangunan yang boleh didirikan ternyata belum ada aturan detailnya, jangankan dalam qanun, bahkan sekedar peraturan bupati yang mengatur apa yang boleh apa yang tidak, juga belum ada.?
Ketika saya tanyakan langsung kepada Bupati yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah ini, saya menangkap kesan kalau dirinya tidak berpikir kalau kebutuhan akan adanya regulasi ini merupakan sesuatu yang penting.
Saya bandingkan dengan Bali, tahun 2010, saya akan membangun sebuah villa untuk seorang klien saya yang berasal dari Amerika. Izin mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten Badung, Bali tak akan dikeluarkan kalau dalam desain eksterior bangunan yang saya ajukan tidak menampilkan minimal 20% arsitektur khas Bali.
Jadi, kalaulah Renggali berlokasi di Bali “pemerkosaan legal” seperti yang dilakukan PT.Grand Arabia pada arsitektur hotel Renggali lama ini tak akan mungkin bisa terjadi.
Lalu apa yang terjadi pada hotel-hotel lain yang dibangun di Aceh Tengah, ya sama saja, tak ada aturan. Pemilik dan investor boleh membangun “kune kenak” tanpa ada rambu-rambu yang mengatur.
Kalau ini tidak segera diatur dan arsitektur “pemerkosaan legal” ini terus berlanjut tak terkendali, jangan heran kalau beberapa tahun dari sekarang sensasi “depaysement” yang menjadi daya tarik utama Gayo untuk dikunjungi perlahan akan menghilang dan Gayo pun menjadi tempat yang terlihat sangat biasa dan tak lagi cukup berharga untuk dikunjungi.
Dan Grand Renggali akan menjadi monumen pengingat untuk anak cucu kita, tentang betapa Gere Berurus-nya kabupaten kita ini. []