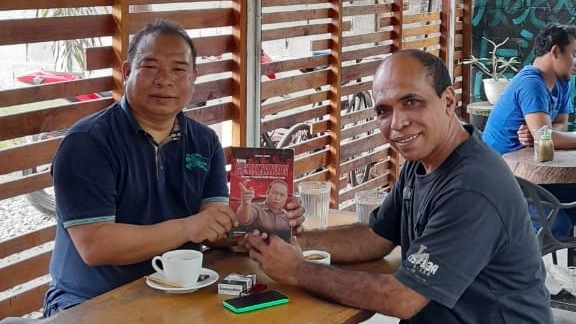Oleh : Fauzan Azima*
BELANDA mengumumkan perang terhadap Aceh, 26 Maret 1873. Dan yang tersisa saat ini di Aceh adalah generasi krisis identitas. Semakin lama, krisis ini semakin kronis. Jika diibaratkan penyakit kanker, level krisis identitas generasi saat ini mencapai stadium empat.
Krisis ini menciptakan generasi yang tidak lagi memahami siapa dirinya. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah memang Allah menciptakan kita sebagai bangsa gagal produk. Secara rupa, mungkin kita manusia. Tapi urusan kelakuan, setiap generasi bangsa ini dalam sekejap bisa berubah dari malaikat menjadi setan.
“Penduduk dunia ini hanya 3 persen yang benar-benar manusia. 97 persen lagi campuran dari bermacam-macam makhluk,” kata seorang teman. “Semacam makhluk hibrida.”
Cara menggolongkan lewat persentase “kemanusiaan” ini memang bias. Tapi pesan yang dapat kita tangkap, hanya sedikit manusia yang menggunakan akal budi dalam hidup dan berkehidupan. Pernyataan itu hanya retorika. Sekadar memancing agar lebih banyak manusia sadar untuk menjaga kelestarian hidup. Pernyataan itu tidak perlu diperdebatkan, sebagai ungkapan benar atau salah.
Pada 1920, Belanda menjadikan kakek moyang kita generasi krisis identitas stadium satu. Kolonialisme dan imperialisme Belanda berhasil menancapkan kuku dan menjalankan sebagian besar misi mereka, yaitu 3G: Gold, Glory dan Gospel. Pengaruh ini menjauhkan masyarakat Aceh dari pengamalan tiga ilmu yang terintegrasi, yakni ilmu kalam, ilmu ghaib dan ilmu musyahadah. Ketiga ilmu tersebut menjadi sumber kekuatan masyarakat Aceh saat itu.
Belanda tahu persis kekuatan ilmu-ilmu itu kalau disatukan. Lantas mereka meluncurkan serangan untuk melemahkan ikatan masyarakat Aceh terhadap ilmu tersebut. Para ahli tarekat, ahli hakikat dan ahli makrifat dikejar dan dibunuh. Di saat yang sama, Belanda mendorong masyarakat untuk mengeramatkan jenis lain dan membangun kefanatikan untuk menutup pikiran-pikiran brilian yang muncul pada masa sebelumnya.
Lantas kadar penyakit pun bertambah. Terlahirlah generasi krisis identitas stadium kedua. Generasi ini dalam bahasa Gayo disebut generasi time rebek atau generasi ember bocor dan dalam bahasa Aceh disebut generasi tima bekah. Ciri khas generasi ini, setiap kali diisi dengan ilmu pengetahuan, otak dan hati mereka tidak pernah mampu mencerna. Semua pengetahuan itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Generasi ini semakin jauh dari nilai-nilai ketauhidan atau ketahudirian. Generasi yang bingung dan penuh keragu-raguan. Generasi yang gagap dan tidak percaya diri.
Generasi time rebek melahirkan generasi gelas kotek atau disebut juga generasi gelas kotor. Seperti air yang dituangkan ke dalam gelas kotor, tidak bisa langsung diminum. Generasi stadium ketiga ini sulit dicarikan obat untuk menyembuhkannya. Ada yang mengatakan penyakit pada generasi ini hanya bisa sembuh lewat “mandi darah” atau perang yang penuh penderitaan. Tetapi hipotesa itu tidak terbukti. Setelah Aceh mengalami beberapa perang besar yang melenyapkan banyak nyawa manusia, namun krisis identitas itu tetap saja mencengkeram generasi.
Dari generasi gelas kotek, lahirlah generasi krisis identitas stadium keempat. Generasi ini seperti tiga butir telur ayam yang masing-masing diberi tanda dengan angka 1, 2 dan 3. Kemudian, ketiga telur itu dipecahkan dan diaduk-aduk menjadi adonan dalam satu wadah. Saat adonan itu diambil sesendok, kita tidak bisa membedakan asal isi sendok; telur 1, 2 atau 3.
Kita yang bertahan hingga saat ini pantas khawatir. Generasi ini sangat mudah dipecah-belah. Hal ini menyebabkan banyak hal. Tidak saja wilayah Aceh yang gampang dicaplok, tetapi isi kepala generasi ini pun “meukeuraleup” atau seperti ada kecoa dalam otaknya.
Tapi masih ada harapan. Berbekal ketiga ilmu di atas, nenek moyang kita seperti meramalkan kemunculan generasi ini sehingga mereka menyediakan serum untuk menyembuhkannya. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak keturunan. Hal ini, dalam bahasa Gayo, disebut tunin inih. Dalam bahasa Aceh dikenal sebagai peusom bijeh. Tradisi mulia ini berupaya menyelamatkan keturunan yang dalam bahasa Gayo disebut enti mate inih atau dalam bahasa Aceh disebut bek mate bijeh.
Orang-orang pintar dan cerdas, orang-orang baik, para guru besar, pejabat-pejabat berotak encer, yang siap lahir dan batin, harus memperbanyak anak. Mereka harus memastikan benih yang mereka miliki terlahir menjadi bibit-bibit unggul. Dan ini lebih mudah jika dilakukan dengan memperbanyak istri sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam Alquran.
Syahdan, dalam sebuah khutbah Idul Adha pertama setelah bencana ganda gempa bumi dan tsunami 2004 di Masjid Baiturrahman, khatib meminta agar bangsa Aceh melahirkan anak keturunan yang banyak untuk menjaga agar generasi Aceh tidak terputus. Enti mate inih atau bek mate bijeh mirip-mirip dengan petuah khatib tersebut.
Nenek moyang kita berkeyakinan bahwa mendistribusikan kebaikan-kebaikan dengan menyebarkan gen dan DNA mereka adalah salah satu cara agar generasi Aceh tidak berkubang dalam lumpur krisis identitas. Terserah, apakah praktik ini dimaknai sebagai upaya para pria Aceh untuk memperbanyak istri atau barangkali ada cara lain untuk memperbanyak keturunan. Memang butuh keberanian ekstra dan strategi jitu untuk melaksanakan niat tersebut. Tapi pada akhirnya, semua pengorbanan itu akan setimpal dengan hasilnya.
Dengan memperbanyak keturunan, maka semakin besar peluang untuk menciptakan generasi unggul, seperti generasi Aceh yang menguasai Asia dan bersahabat dekat dengan Kerajaan Turki Usmani.
Kita kerap mengeluhkan bahwa bangsa-bangsa asing, “Israel Barat” atau “Israel Timur” menjajah dan menguasai anak negeri ini dari sisi politik, ekonomi, kedaulatan dan pikiran. Namun kita tidak boleh menyalahkan pihak lain sementara kita tidak mengorganisir diri untuk menelurkan kepintaran, kesalehan, kecemerlangan, keagungan, kehebatan dan kesempurnaan. Kita tidak boleh ragu untuk meyakinkan kaum hawa saat mereka menentang niat ini, walaupun dengan lantang mereka berkata, “langkahi dulu mayatku!”
Saya tak ingin menyamaratakan. Namun sejarah mencatat kematian tetap mendatangi siapa saja, entah itu pemberani atau pengecut. Sejarah juga bakal mencatat, apakah kita termasuk pria yang memilih untuk menjalankan prinsip atau pria yang memilih untuk bersembunyi dan mengabaikan tanggung jawab besar; melahirkan generasi yang lebih baik.
Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi penakut. Jangan mengira menjadi pengecut tidak dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mengapa harus takut berbuat mulia? Justru ketakutan merusak tatanan kehidupan di dunia yang seharusnya diisi dengan manusia-manusia berkualitas. Lewat peraduan yang halal.
Tidak perlu takut. Orang berani bukan yang tidak memiliki rasa takut. Para pemberani adalah orang-orang yang mampu mengatasi rasa takut. Dalam hidup, kita harus memiliki keyakinan. Kalau kita yakin, dan itu ternyata salah, maka kita mendapat satu pahala, yaitu pahala keyakinan. Selanjutnya kalau kita yakin dan itu benar, maka kita beroleh dua pahala, keyakinan dan kebenaran.
Sebagai “panglima”, kita, para pria, bertanggung jawab untuk mencegah generasi agar tidak tersesat pada krisis identitas. Yakinkan istri masing-masing bahwa kemuliaan hanya bisa didapat lewat pengorbanan. Karena dalam urusan ini, sering kali pria dianggap “mau enak sendiri” dan wanita harus berkorban. Dalam perkara ini, pria juga berkorban.
Betapa jahat pejabat dan pengusaha sukses yang ke luar daerah hanya untuk “jajan”. Bahkan tingkat orang terhormat di negeri kita menganggap perjalanan ke luar kota adalah saat untuk memasuki zona bebas sehingga dengan mudah berkata, “I want to order one hotdog, one beer.” Sikap ini tidak perlu terjadi kalau ada keterbukaan. Jadi, semua kita harus bersikap ksatria dan jangan pernah bergerilya untuk “jajan”.
Letnan Jenderal Doni Monardo, bekas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, saat memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, mengungkap pandangan umum masyarakat bahwa kebiasaan memakan daging kambing menjadi sumber penyakit asam urat, kolesterol dan darah tinggi.
Namun dia dengan lantang berujar, “jangan salahkan kari kambing. Salahkan diri yang tidak mau berolah raga.”
“Ike kenak mujadi panglime, tehen anak ni bedil”. Frasa dalam bahasa Gayo itu berarti “kalau ingin menjadi panglima, harus mampu menahan peluru”. Pesan itu disampaikan oleh Tengku Ilyas Leube, salah satu pejuang Aceh yang tersohor.
Pada cerita lain, seorang lelaki Arab membuat pengajian di Jalan Sudirman, Banda Aceh. Dia membawa serta semua istrinya. Semua istri, tentu saja ini lebih dari satu. Ibu-ibu yang mengikuti pengajian itu dengan heran bertanya kepada istri-istri orang Arab itu lewat penerjemah.
“Mengapa kalian mau dimadu?”
“Saya sendiri tidak sanggup melayani suami saya, jadi harus bergiliran,” jawab istri orang Arab itu. Ibu-ibu yang penasaran tercengang.
Saya pernah melihat pada salah satu restoran di Jakarta, dua lelaki Arab menghabiskan satu ekor kambing. Artinya keinginan untuk memperbanyak generasi juga harus dibarengi dengan gizi tinggi, kesiapan fisik dan mental. Sehingga, seperti orang Arab itu, dia tidak perlu meminta menikah lagi. Istrinya yang memberikan lampu hijau untuk suaminya meminang wanita lain.
Satu hal yang penting untuk diingat, agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang berbilang istri, amanahkan pada “biji kelereng” masing-masing. Sampaikan padanya, “amanlah engkau polin dengan polin sebagaimana aman biji kelereng ini.” Dan setiap mendatangi istri, amanahkan juga sambil mencucinya, “kawan, malam ini lawan berat. Jangan buat malu.”
(Mendale, Desember 8, 2022)