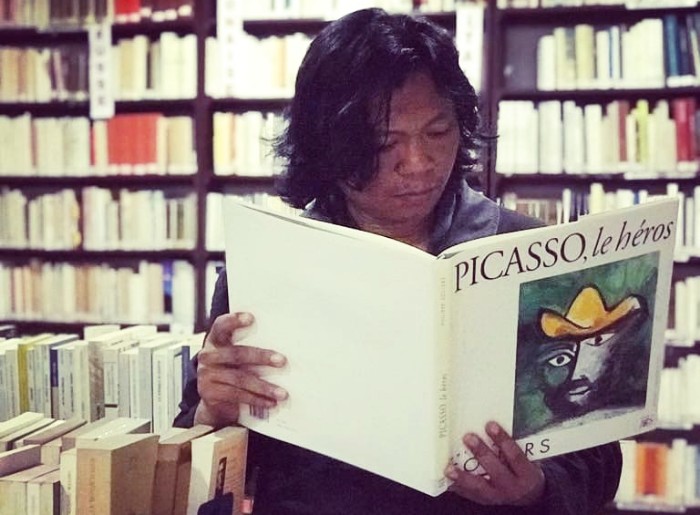Catatan : Win Wan Nur*
Akhir desember 2020 yang baru saja kita tinggalkan beberapa waktu yang lalu, di Banda Aceh saya mendengar kabar kalau teman sekelas saya waktu di SMA Negeri 2 Banda Aceh yang sekarang berdomisili di Philipina juga sedang berada di kota ini. Lama tidak berjumpa, kami kemudian membuat janji bertemu di Café Montes, Lampineung.
Teman saya yang menamatkan S1 nya di Jogja ini, dulunya adalah tokoh penting gerakan mahasiswa yang membidani lahirnya SIRA dan juga berperan penting dalam merancang perdamaian Aceh.
Pasca tsunami, setelah sempat bekerja di BRR, teman saya ini kemudian melanjutkan S3 di salah satu negara Skandinavia dan kemudian fokus bekerja di NGO yang terkait dengan perdamaian. Setelah sempat lama bekerja di Myanmar terkait Rohingya, saat ini dia berkantor di Philipina dengan fokus utama menjembatani perdamaian antara pemberontak Moro dengan pemerintah Philipina.
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga tersebut, teman ini juga sering diundang berbicara di berbagai forum Internasional, sering diundang menjadi dosen tamu di pelbagai universitas di dunia, yang paling sering di Asia, Inggris, Eropa dan Amerika.
Berbicara panjang lebar, pembicaraan kami sampai pada kontroversi Bank Syari’ah versus Bank Konvensional. Kepada teman ini, saya mengatakan kalau pelarangan operasi bank konvensional ini menimbulkan kesulitan dan merugikan pelaku usaha kopi di Gayo. Mendengar itu, tiba-tiba suara teman saya ini meninggi.
“Kalo bicara dirugikan, saya yang paling dirugikan dengan kebijakan tidak jelas ini,” katanya lantang. “Kok bisa?” Tanya saya.
Lalu diapun menjelaskan kalau selama ini, meskipun dia berdomisili di Philipina, tetapi tiap kali ada waktu libur dan cuti, dia selalu memanfaatkan dan menghabiskan waktu liburnya di Aceh.
Kalaupun dia harus ke Jakarta atau Medan, itu hanya dia lakukan untuk urusan kerja. Karena itulah, semua gaji dan honor yang dia terima masuk ke rekeningnya di BRI. Dengan begitu kalau dia berada di Aceh, dia bisa bebas menarik uangnya untuk keperluan apapun.
Karena penghasilan yang dia terima dalam bentuk mata uang asing, dia membuka rekening dalam 4 mata uang, GBP (Poundsterling Inggris), Euro, US Dollar dan Rupiah. Rekening rupiah, yang paling sedikit isinya karena hanya dia pakai untuk membayar kartu kredit.
Emosinya meninggi saat bicara larangan beroperasinya bank konvensional, karena menurutnya bank syari’ah tidak bisa mengakomodir permasalahannya. Tidak seperti BRI konvensional, untuk rekening yang menggunakan valuta asing, bank syari’ah hanya mengakomodir dollar.
Artinya, kalau dia menerima honor dalam mata uang Poundsterling dan Euro, uangnya itu harus dikonversi dulu menjadi dollar Amerika dan kemudian kalau mau dirupiahkan, harus dikonversi kembali ke rupiah, sehingga dia rugi dua kali selisih harga jual dan beli dalam transaksi.
Kalau dia tetap menggunakan BRI konvensional, seandainya ada permasalahan yang harus dia selesaikan terkait rekeningnya, entah itu uang transfer belum masuk, atau kartu ATM hilang, dia tidak bisa lagi mengurusnya di Aceh. Paling dekat dia harus terbang ke Medan.
Sebelumnya, di Takengen, saya berbicara dengan teman-teman para pedagang kopi. Mereka juga mengeluh dengan kebijakan yang menurut mereka tidak bijak ini. Kata mereka, sebagai pedagang, mereka bukan anti bank syari’ah, tapi masalahnya beban yang harus mereka bayar seandainya berpartner dengan bank syari’ah, jauh lebih besar dibandingkan bank konvensional.
Sebagai contoh, kalau mereka mengambil kredit di BRI konvensional, ada fasilitas KUR yang memberi bunga ringan ‘hanya’ 6% per tahun. Sementara, kalau bekerjasama dengan BRI syari’ah, untuk bisa mendapatkan kredit, memang mereka mendapat keistimewaan untuk melakukan perjanjian akad layaknya pernikahan dan istilah bunga diganti dengan istilah akad musyarakah, sehingga katanya kredit mereka menjadi halal tapi harga yang harus mereka bayar untuk penggantian istilah tersebut tidaklah kecil, setidaknya 15% per tahun.
Yang artinya hampir tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan jika mereka mengambil kredit KUR di BRI konvensional. Dari penjelasannya ini, sayapun bisa memahami pernyataan “Orang Gayo sebenarnya tidak peduli apakah bank itu syari’ah atau konvensional, mana yang memberi bunga murah, ke sana mereka meminjam,” yang diucapkan bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar di depan delegasi kemenkop yang hadir di Gayo beberapa waktu yang lalu.
Tidak hanya nasabah dan pelaku usaha, kontroversi pelarangan beroperasinya bank konvensional di Aceh juga membuat kalang kabut para pekerja bank konvensional di provinsi ini. Para pekerja ini dipaksa harus memilih, tinggal di Aceh dan pindah bekerja ke bank syari’ah dengan penghasilan dipotong 35%, atau tetap di bank konvensional tapi harus pindah ke provinsi lain.
Kebanyakan akhirnya memilih untuk pindah ke provinsi lain. Salah satu dari para pekerja bank tersebut adalah sepupu saya sendiri.
Menurut sepupu saya ini, sebenarnya dia lebih suka bekerja di Aceh, karena dekat dengan keluarga dan dia juga bisa menemani dua orangtuanya yang sudah pensiun. Tapi masalahnya, di samping soal penghasilan yang dipotong 35% yang akan membuatnya kesulitan membiayai cicilan rumah, mobil dan pendidikan tiga anaknya, dia juga merasa tidak nyaman bekerja di bank syari’ah karena setiap hari harus menghadapi komplain nasabah.
“Bank syari’ah memiliki server yang berbeda dengan bank konvensional,” katanya.
Kemudian dia menjelaskan bagaimana panjangnya daftar keluhan nasabah bank syari’ah soal ATM yang lelet, rekening sudah terdebit tapi uang tidak keluar, transfer yang tidak sampai (saya mengalami sendiri hampir 10 tahun yang lalu, transfer dari bank Aceh ke BRI, uang sudah terdebit tapi uangnya belum masuk ke rekening saya sampai hari ini) dan seterusnya.
Menurut sepupu saya ini, tahun 2020 lalu dari januari sampai oktober saja sudah ada 1,5 juta komplain yang masuk ke BRI syari’ah.
Bagi pembaca di luar Aceh mungkin bertanya-tanya, kalau begitu banyak kesulitan yang dihadapi dengan perbankan syari’ah, kenapa sistem ini dipaksakan melakukan monopoli jasa perbankan di Aceh.
Jawabannya adalah Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 4 Januari 2018 dan wajib diberlakukan 3 tahun setelah disahkan, yang artinya tanggal 4 januari 2021 ini.
Sebenarnya, di Qanun ini secara eksplisit tidak ada larangan atas beroperasinya lembaga keuangan konvensional. Tapi mungkin karena di pasal 2 qanun ini dikatakan bahwa “lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syari’ah” ini diartikan sebagai lembaga keuangan konvensional tak boleh beroperasi lagi di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.
Lalu, ada apa sebenarnya dengan bank konvensional sehingga tidak boleh ada di Aceh?
Penyebabnya adalah hukum Islam yang mengharamkan riba, semua ulama dari semua mazhab dalam Islam sepakat bahwa, sebagaimana babi, riba adalah haram. Aceh sebagai provinsi pengusung syari’at Islam tentu tidak mau membiarkan warganya hidup dengan mengkonsumsi ‘produk’ yang diharamkan oleh ajaran Islam.
Tapi kalau ini alasannya, kemudian muncul pertanyaan, kalau riba haram, kenapa di banyak negara Islam termasuk Arab Saudi yang jelas-jelas menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukumnya masih menerima bank konvensional dan masih bertransaksi dengan bank konvensional yang memberikan bunga.
Nah di sinilah letak masalahnya. Yang menjadi perdebatan di sini, tidak seperti babi yang jelas wujudnya, yang tak ada sedikitpun kontroversi tentang esensinya, bunga bank membuka begitu banyak tafsir. Ada yang ulama, sebut saja seperti Syeikh bin Baz dari Arab Saudi, Dr. Yusuf Al-Qaradawy dan gurunya Syeikh Abu Zahrah dari Al Azhar yang memandang bunga bank itu sebagai riba yang artinya haram.
Tapi selain mereka, tidak sedikit juga ulama, sebut saja seperti Dr. Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abdul al-Wahab Khallaf dan juga Syeikh Mahmud Shaltut yang memandang bunga bank lebih cenderung sebagai pembagian hasil keuntungan usaha, yang artinya halal.
Mufti resmi negara Mesir, Syeikh Dr. Ali Jum’ah juga cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan juga fatwa resmi Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Pernyataan ini sengaja beliau tekankan untuk menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkan bahwa keharaman bunga bank itu sudah menjadi ijma’ jumhur ulama.
Artinya, berbeda dengan Babi yang tak ada keraguan sedikitpun tentang keharamananya. Sebenarnya kalau kita ikuti perdebatan para ulama terkait riba tidaknya bunga bank, ini mirip-mirip seperti perdebatan tentang haramnya bid’ah. Semua ulama sepakat bahwa bid’ah itu haram, tapi mereka berbeda pandangan tentang apa saja yang dikategorikan sebagai bid’ah, sehingga muncullah istilah khilafiyah.
Riba atau tidaknya bunga bank juga sama, masih merupakan khilafiyah dan belum final.
Kemudian, kalaupun bunga bank harus dianggap riba yang kalau kita telusuri akar katanya adalah “bertambah” atau “bertumbuh”, bukankah bank syari’ah juga memberikan penambahan itu, meskipun istilahnya diganti menjadi berbahasa arab dan prosedurnya dibuat lebih rumit. Pada intinya, uang yang ada di sana bertambah dan uang yang dipinjam juga bertambah.
Karena pada intinya tak banyak berbeda dengan konsep bunga di bank konvensional, sering kita mendengar bahwa “bunga” di bank syari’ah jadi halal karena ada akad dengan menganalogikan pada konsep perkawinan yang membuat hubungan seksual jadi halal. Tapi logika seperti ini kelihatannya dikarang baru-baru ini saja, karena memang tak ada presedennya di masa awal-awal Islam baru berkembang.
Mendapati kenyataan seperti ini, mempertimbangkan besarnya dampak negatif dari segi ekonomi yang harus dihadapi oleh Aceh ketika sistem perbankan syari’ah yang masih sangat belum siap dengan solusi untuk berbagai persoalan dan masalah dalam transaksi keuangan modern.
Menjadi wajar kalau Nova Iriansyah selaku gubernur Aceh yang bertanggung jawab atas hajat hidup dan kesejahteraan rakyat Aceh meminta penundaan penerapan bank syari’ah untuk memonopoli sistem perbankan Aceh.
Tapi sayangnya, karena masyarakat Aceh begitu besar ghirahnya dalam beragama dan isu soal syari’ah ini sudah dikaitkan dengan agama dan opini yang mendominasi ruang pikir publik Aceh adalah bank konvensional haram dan bank syari’ah halal. Segala fakta bahwa riba atau bukannya bunga bank masih menjadi khilafiyah dan belum menjadi ijma’ jumhur ulama. Tak mau mereka dengar.
Pokoknya, yang menolak monopoli bank syari’ah mereka citrakan sebagai orang yang menolak syari’at Islam bahkan anti Islam.
Kalau kita lihat berbagai komentar di media sosial, label inilah yang dilekatkan pada Nova Iriansyah yang berniat melindungi kepentingan warganya. Dia disebut tidak mendukung syari’at Islam, bahkan ada yang menyebutnya musuh Islam.
Sialnya, karena Nova bersuku Gayo yang minoritas, label ini tak hanya berhenti di Nova, tak sedikit yang berkomentar di dunia maya membawa-bawa asal sukunya dengan mencitrakan bahwa orang Gayo memang anti Islam.
Fenomena ini mengingatkan saya pada ucapan Ibnu Rushd yang mengatakan :
“Jika Ingin Menguasai Orang Bodoh, Bungkus Sesuatu yang Batil dengan Agama”
Dalam konteks kekinian, ucapan Ibnu Rushd ini bisa kita maknai dengan
“Jika ingin memonopoli pasar dengan produk berkualitas rendah tapi mahal, bungkuslah produk itu dengan kemasan agama.”
*Dewan Redaksi LintasGAYO.co