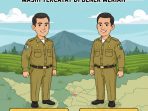Oleh : Nanda Winar Sagita*
Saya masih ingat: waktu masih mahasiswa, kami sempat berdebat tentang hakikat ilmu sejarah. Disatu sisi, ada yang percaya bahwa sejarah itu ilmu pasti dan tidak boleh diganggu gugat karena sudah melalui proses metodologi yang runtut sebelum dituliskan; sedangkan disisi lain, ada yang yakin sejarah itu sekedar ilmu yang masih buram dan akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Tentu saja saya ada di sisi kedua, karena saya masih percaya: sejarah sejatinya hanya bias dari penulis yang tidak bisa menghindar dari godaan subjektifitas.
Untuk menyebut satu contoh saja, selama bertahun-tahun Indonesia selalu terpaku pada satu sejarah tunggal versi Pemerintah. Secara khusus, sejarah yang dimaksud adalah tragedi kekerasan pasca 1965.
Dalam kasus tersebut, tentu saja posisi Orde Baru senantiasa dijadikan sebagai pahlawan tunggal, dengan mengenyampingkan peran dari banyak pihak—bahkan dalam hal ini peran dari kubu Soekarno.
Siapa pun mahasiswa sejarah pasti mengenal buku karangan Nugroho Notosusanto yang senantiasa dijadikan sebagai referensi tunggal dalam mempelajari sejarah, baik di kampus-kampus maupun di sekolah.
Baru setelah era Reformasi dimulai, buku itu mulai ditinggalkan secara perlahan lantaran bias subjektif “menjilat pemerintah” yang tertera di sana memang tidak bisa dibantah. Hal itu wajar, lantaran penulisnya sendiri pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Pemerintahan Soeharto.
Bicara tentang sejarah Gayo, khususnya Kerajaan Linge, tentu harus kita akui bahwa belum banyak (atau malah belum ada?) referensi akurat yang membahas tentang eksistensi kerajaan tersebut. Hal itu saya katakan karena bertolak pada adagium masyhur yang kerap digaung-gaungkan oleh para sejarawan modern: no document, no history.
Soal Kerajaan Linge, sejauh ini kita hanya berasal dari cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun, dan kebetulan beberapa penulis asal Gayo sempat menulis ulang hasil dari cerita tersebut dengan bias subjektif yang tidak bisa dihindari.
Satu buku yang paling lawas yang membahas eksistensi Linge adalah Sejarah Daerah dan Suku Gayo karangan Abdurrahim Daudy. Buku ini pertama diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1979. Sebelumnya, buku ini diterbitkan secara stensilan oleh Dokumentasi L.K Ara pada 1971.
Kalau saya tidak keliru, narasi dalam buku ini juga yang menjadi acuan Dr. Yusra Habib Abdul Gani dalam menulis dua bukunya yang membahas tentang Linge: Gayo dan Kerajaan Linge (2020).
Dalam buku tersebut, sejarah diceritakan melalui bentuk syair berbahasa Gayo. Inti yang bisa disimpulkan soal awal mula Kerajaan Linge adalah seperti ini: di negeri Rum (kemungkinan maksudnya Turki) hiduplah dua orang saudara.
Abangnya adalah rakyat jelata yang punya tujuh putra, adiknya adalah raja yang punya tujuh putri. Pada suatu hari ketujuh putra si abang meminta agar dibuatkan kail. Singkat cerita, belum selesai satu kail dibuat salah seorang putranya yang bernama Adi Genali sudah pergi terlebih dahulu ke laut dan tersesat hingga terdampar di suatu pulau.
Pulau yang dimaksud itulah yang sekarang dikenal dengan Buntul Linge, dan di sanalah dia mendirikan sebuah kerajaan yang kita kenal dengan Kerajaan Linge.
Cerita yang tertulis di buku itu jauh lebih kompleks dari yang saya tuliskan, tapi sekadar pengantar begitulah awal Kerajaan Linge yang dipercayai secara turun-temurun dan ditulis secara berulang-ulang.
Tentu saja ada satu masalah krusial yang jarang disentuh oleh kita, yakni semua yang tertulis di buku itu tidak punya referensi yang akurat. Kita tahu bagaimana eksistensi kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara bisa terbaca jelas melalui prasasti atau kerajaan Islam yang tertulis melalui hikayat-hikayat, tapi tidak untuk Kerajaan Linge.
Bahkan dalam catatan perjalanan penjelajah asing seperti Marcopolo atau Ibn Batutta pun Kerajaan Linge tidak disebutkan. Dari bukti berupa nisan dan cerita lisan yang kita kenal, kita memang tidak menampik bahwa Kerajaan Linge itu ada, tapi bagaimana pun juga sebagian dari kita masih skeptis dan kritis apakah memang benar kejayaannya seperti yang kita yakini sekarang.
Adapun pertanyaan lanjutannya adalah seperti ini: lantas bagaimana seharusnya sejarah Gayo ditulis?
Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana metodologi sejarah yang baik. Sudah menjadi pengetahuan umum, menulis teks sejarah itu bukan sekadar berdongeng atau ngelantur sebagaimana menulis teks fiksi seperti novel atau cerita pendek.
Ada empat tahap yang harus diketahui tentang metode penulisan sejarah, yakni Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.
Heuristik adalah proses pengumpulan bukti sejarah; baik berupa dokumen, artefak, prasasti, fosil, atau bahkan cerita lisan. Verifikasi adalah proses mengkritik sumber atau menguji keaslian dan kredibelitasnya.
Interprestasi adalah proses menganalisis sumber dengan cara membandingkannya sumber tersebut dengan fakta yang sudah absah dan akurat. Terakhir, historiografi adalah proses penulisan sejarah dengan hanya terfokus pada sumber-sumber yang sesuai dengan fakta atau rasional.
Tapi masalah penulis sejarah Gayo yang sudah ada kerap kali melewati proses verifikasi dan interpretasi, dua proses yang sangat penting, karena langsung meloncat dari heuristik ke historiografi.
Hal itulah yang menyebabkan sejarah Gayo, khususnya tentang Kerajaan Linge, masih dibumbui dengan dongeng dan legenda yang sebenarnya tidak masuk akal dan melebihi keajaiban kisah-kisah para nabi yang tertera di kitab suci.
Soal rasionalitas penulisan sejarah itu penting, agar kita tidak terjebak dalam dongeng selama bertahun-tahun dan mewariskannya pula pada penerus kita nanti. Hegel, filsuf masyhur dari Jerman, pernah menulis begini: “satu-satunya gagasan yang dibawa oleh filsafat yang berkaitan dengan sejarah adalah gagasan sederhana tentang rasio, dan dengan demikian sejarah tentu harus rasional atau masuk akal.”
Hegel juga bilang kalau legenda, lagu-lagu rakyat, dan berbagai ragam tradisi, tidak bisa dianggap sebagai sumber untuk menentukan asal-muasal sejarah, karena semua itu tidak jelas dan mengaburkan berbagai metode sejarah, atau dengan kata lain semua itu hanya warisan mentalitas masyarakat yang buta huruf (ini bukan pernyataan saya, tapi bisa dibaca dalam buku Hegel Introduction of the Philosophy of History yang sudah diterjemahkan menjadi Filsafat Sejarah, terbitan Panta Rhei Books tahun 2003).
Bersandar pada penjelasan di atas, sejatinya kita sudah tahu jawaban dari pertanyaan “bagaimana seharusnya sejarah Gayo ditulis?”. Tidak ada cara lain untuk membuat tingkat keilmuan sejarah kita menjadi rasional dan agung, selain bersandar pada metode-metode sejarah yang sudah saya sebutkan.
Tentu bias sebagai Orang Gayo memang tidak bisa dihindari, tapi kita berupaya untuk mengurangi. Kita tidak perlu sungkan untuk menulis sejarah dengan perspektif yang berbeda dari pemahaman orang kebanyakan, asalkan kita punya sandaran yang logis.
Sekali lagi saya ulangi dan tekankan: kita memang tidak menampik bahwa Kerajaan Linge itu ada, tapi bagaimana pun juga sebagian dari kita masih skeptis dan kritis apakah memang benar kejayaannya seperti yang kita yakini sekarang.
Oleh sebab itu, mari kita mulai penulisan sejarah dengan cara yang ilmiah. Kita memang tidak perlu mengesampingkan keyakinan bahwa pada dasarnya di masa lalu orang Gayo memang benar-benar punya peradaban yang gemilang, tapi tidak harus membesar-besarkan hal yang tidak perlu.
Lagi pula, seiring waktu dan penemuan sumber-sumber baru, bisa jadi sejarah yang kita tuliskan sekarang akan berubah di masa yang akan datang. []