[Cerpen]
(Ini Kenyataan yang Pahit dan Kepahitan Yang Nyata)
Karya: Teuku Afifuddin
Bag. 2
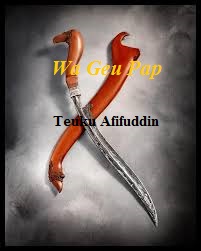 Aku yang bau kencur berkerut dahi. Bingung dan bangai, melihat polah dari dua sisi yang berbeda. Dipojok kantin yang hampir bangkrut aku lemas, otakku mulai lelah dengan realita ini, hingga aku tertidur pulas oleh asap sebatang pateng yang merayap ke hidungku. Aku tergeletak di sudut kantin, sayup-sayup terdengar seseorang membaca puisi. Hanya kalimat terakhir yang mampu ku rekam. “Siapa yang menghamili rembulan” Ah, gedung ini telah banyak menyimpan kepedihan.
Aku yang bau kencur berkerut dahi. Bingung dan bangai, melihat polah dari dua sisi yang berbeda. Dipojok kantin yang hampir bangkrut aku lemas, otakku mulai lelah dengan realita ini, hingga aku tertidur pulas oleh asap sebatang pateng yang merayap ke hidungku. Aku tergeletak di sudut kantin, sayup-sayup terdengar seseorang membaca puisi. Hanya kalimat terakhir yang mampu ku rekam. “Siapa yang menghamili rembulan” Ah, gedung ini telah banyak menyimpan kepedihan.
“Bila aku memikirkan kepedihan ini, maka kepedihan tak akan pernah pergi , baiknya aku menghayal saja tentang kebahagiaan agar segera singgah” aku bergumam. Bagaimana tidak, aku teringat dengan petuah orang tua di kampung
“Nak, orang-orang sukses itu semuanya diawali dengan kepedihan, mereka beranjak sukses dengan menghadapi kepedihan itu, bukan lari” begitu nasehat kakekku ketika aku mengeluh tentang kondisi negeri yang tak kunjung reda dengan yang namanya konflik. Bila aku mengingat petuah itu, kenapa harus galau dengan kenyataan yang sedang ku hadapi ini? Ini memang kenyataan pahit dan kepahitan yang nyata. Saat mentari mulai bersinar hingga bulan menghalanginya, namun kita belum makan dan kematianpun tak menghampiri. Adakah ketakutan yang harus ditakuti melebihi kematian? Ah, masa-masa itu sudah berlalu, namun gedung ini masih seperti dulu, selalu menjadi korban bandit-bandit anggaran. Sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamku.
“Sudah sampai di negeri dibawah angin teman?” pesan itu dari seorang teman karibku. Tanpa memberi jeda yang lama, aku langsung menghubunginya.
“Aku sudah sampai di negeri dibawah angin, kawan” Ucapku dengan lantang layaknya seorang deklamator puisi. “Dimana engkau kini teman” Lanjutku. Lama ia baru menjawab
“Aku sedang meneguk secangkir kopi teman” lalu melanjutkan kalimatnya dengan menyebut sebuah nama warung kopi yang sering kami singgahi untuk diskusi, sambil menikmati jaringan internet gratis.
“Apa kegiatanmu sekarang? Dan bagaimana dengan sanggarmu sobat?”. Dia kembali memberi jeda pada dialognya.
“Aku sudah pensiun kawan!” terdengar lemas dari seberang telepon genggamku. Jantungku seperti berhenti berdegup mendengar ucapan seorang teman yang dahulu mendukungku untuk melanjutkan pendidikan di ranah urang. Ingatanku langsung tertuju pada kalimat yang pernah diucapkan dosenku saat perkuliahan dulu.
“ Sebagai PNS saya boleh pensiun, tapi sebagai seniman tidak!” ucap Profesor itu.
Sepertinya, kondisi hati temanku sama seperti kondisi gedung ini, sehingga dengan berat hati ia menyatakan pensiun. Atau mungkin kondisi di nanggroe ini yang membuatnya berucap begitu, atau?
“Teman, aku tunggu engkau di bawah pohon keupula” menutup pembicaraan kami.
Ah, nanggroe ini sudah banyak sekali berubah, mulai dari bangunannya sampai mental rakyat. Mulai dari supir taksi dengan logat daerahnya memanggilku Mas, gedung yang tercerai dari pertunjukannya sampai seorang teman yang putus asa. Seperti apa yang kulihat kini, gedung telah bercerai dengan pertunjukan dan penontonnya. Orang-orang telah beralih ke gedung-gedung beraroma kopi, disana mereka dapat menyaksikan sekaligus bermain dalam drama tanpa babak dipertunjukan tanpa judul. Ah, mereka bersandar dikursi empuk sambil menyimak persegi berkilau dan bersuara. Ah! Semua telah berubah.
Sekarang orang-orang berjuang mencari pembenaran diri daripada mencari kebenaran. Sehingga yang dilakukan harus diakui kebenarannya oleh banyak orang. Dulu laki-laki bertatto akan dinilai sebagai preman dan pasti jahat. Waktu kecil, saat aku dan mak pergi ke Peukan, Mak pernah menarik tanganku sambil berucap.
“Ayo cepat kita pergi” kata mak,
“Tapi aku masih ingin nonton PM TOH” jawabku sambil merengek.
PM TOH adalah sebutan untuk kesenian yang dibawa oleh Tengku Adnan PM TOH. Saat itu Teungku Adnan sering memainkannya di pasar pada hari peukan sambil kemudian menjual obat yang dibawanya. Kesenian itu sebenarnya bernama Dangdeuria atau disebut juga dengan Teater Tutur. Itupun baru aku tahu ketika aku menempuh perkuliahan di ranah urang.
“Ayo cepat ada bandit” mak menakuti ku sambil menarik tangan.
“Mana, gak ada”
“Itu, yang tangannya penuh gambar” mak menunjuk ke arah laki-laki bertatto
Begitu aku melihat kearah lelaki bertatto itu, aku langsung memeluk kaki mak dan menangis ketakutan. Begitu buruknya pandangan orang terhadap yang bertatto masa itu. Bagiku saat itu seperti melihat monster yang ada di film kartun.
Tapi sekarang tidak lagi, setelah ada pembenaran bahwa tatto itu merupakan gaya penampilan, bahkan ada yang memberi pembenaran dengan menyebutnya sebuah bentuk ekspresi seni. Begitu juga dengan yang namanya korupsi. Kini korupsi sudah mulai disebut budaya atau tradisi. Karena sudah semakin banyak yang melakukannya dan pelakunya membuat alibi pembenaran untuk hal yang dilakukan. Seperti salah satu alibi yang pernah kudengar dari pelayan negeriku, saat itu, aku sedang mengurus surat-surat penting untuk kuliah. Seorang pria berkumis tebal yang melayaniku, di akhir layanannya dia meminta uang receh dariku.
“Dek ini suratnya sudah selesai, biayanya terserah adek, se-ikhlasnya saja” dia berucap sambil menghisap sebatang rokok yang asapnya terbang melewati tulisan ruangan tanpa asap rokok.
Aku saat itu kaget dan bingung, sebelum masuk ke gedung itu aku melihat pengumuman yang bertuliskan seluruh pengurusan tidak dikenakan biaya dan tidak menggunakan calo.
“Lho kok bayar pak, tapi diluar tertulis kalau segala pengurusan tidak di pungut bayaran” sanggahku
“Dek, jaman sekarang mana ada yang gak pakek bayar, mau jadi PNS harus bayar, mau jadi upah harus bayar bahkan untuk jadi presidenpun harus bayar. Ya bayar rakyat, atau bahasa kerennya money politik. Dek, Peraturan itu dibuat untuk dilanggar” jawabnya sambil menunjukkan kotak tempat memasukkan recehan administrasi.
Wah gawat kalau seperti penjelasan bapak berkumis itu. Bila dilihat dari alibinya, korupsi sudah membudaya dari mulai presiden sampai pelayan negeri bahkan rakyat. Jangan-jangan nanti korupsi akan disebut seni, dan gedung ini salah satu karya seni tersebut, seni korupsi! Telepon genggamku kembali berbunyi, pertanda ada pesan singkat yang masuk.
“Teman, aku sudah dibawah pohon keupula”. Memang dengan berat hati aku harus meninggalkan pentas usang ini. Sambil berjalan aku berteriak.
“Wa Geu Pap” [TAMAT]
Catatan :
Wa Geu Pap (Bahasa Aceh) : Ungkapan kekesalan
tanoh indatu (Bahasa Aceh) : Tanah nenek monyang
pohon keupula (Bahasa Aceh) : Pohon Tanjung
ranah urang (Bahasa Minang) : Tanah Orang
peukan (Bahasa Aceh) : Pasar
 Teuku Afifuddin dikenal dengan Teuku Afeed. Lahir di langsa, 16 Juni 1982. Suami dari Juriawati, SH dan Ayah Cut Azalea Syadza. Pemilik KTP dengan pekerjaan Seniman. Editor Film Dokumenter diantaranya The tsunami song, silent after war, musik tanpa bunyi dan beberapa FTV. Film Dokumenter Karya editingnya “The Tsunami Song” menerima penghargaan terbaik Festival Film Dokumenter-Jogja 2005. Film dokumenter pendek pertamanya “Pujangga Tanpa Pikir (Adnan PM TOH)” menjadi film terbaik II Pekan Seni Mahasiswa-Lampung 2004. Mulai menulis Puisi sejak menjadi mahasiswa FKIP Sendratasik jurusan musik Unsyiah 2000. Puisi yang di tulisnya ditempelkan di dinding kampus. Semasa kuliah di Unsyiah Aktif di UKM Teater NOL dan Teater MATA. Pemeran Khep pada naskah “JEEH!” Karya Almarhum Maskirbi.
Teuku Afifuddin dikenal dengan Teuku Afeed. Lahir di langsa, 16 Juni 1982. Suami dari Juriawati, SH dan Ayah Cut Azalea Syadza. Pemilik KTP dengan pekerjaan Seniman. Editor Film Dokumenter diantaranya The tsunami song, silent after war, musik tanpa bunyi dan beberapa FTV. Film Dokumenter Karya editingnya “The Tsunami Song” menerima penghargaan terbaik Festival Film Dokumenter-Jogja 2005. Film dokumenter pendek pertamanya “Pujangga Tanpa Pikir (Adnan PM TOH)” menjadi film terbaik II Pekan Seni Mahasiswa-Lampung 2004. Mulai menulis Puisi sejak menjadi mahasiswa FKIP Sendratasik jurusan musik Unsyiah 2000. Puisi yang di tulisnya ditempelkan di dinding kampus. Semasa kuliah di Unsyiah Aktif di UKM Teater NOL dan Teater MATA. Pemeran Khep pada naskah “JEEH!” Karya Almarhum Maskirbi.
Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kesenian Aceh pada tahun 2007. Pada tahun yang sama mendesign 10 sampul buku karya sastra terbitan Aliansi Sastrawan Aceh. TIM Pendiri Institut Seni dan Budaya Indonesia Termuda ini adalah pencinta tradisi, mampu menabuh rapa’i, dan lihai menepuk bantal didong. Mahasiswa Prodi Pengkajian Seni Pascasarjana ISI Padangpanjang. Selain itu kini menekuni pekerjaan sebagai Dramaturg Teater. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Pengkajian Teater Institut Seni Indonesia Padangpanjang. [SY]



















