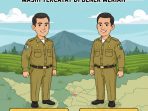Oleh : Win Wan Nur*
Hari-hari belakangan ini dunia yang baru dilanda kehebohan akibat diserangnya kantor majalah Charlie Hebdo, sebuah majalah mingguan yang terbit di Perancis yang mengkhususkan diri pada kartun-kartun satir kasar untuk menyindir para pemimpin politik dan agama. Serangan itu menewaskan 12 orang yang 2 orang di antaranya adalah polisi. Yang salah satunya beragama Islam.
Peristiwa ini serentak mengundang simpati dunia. Di Twitter tagline #JeSuisCharlie (Saya Adalah Charlie) segera menjadi trend topic. Di seluruh dunia orang turun ke jalan membawa poster dan spanduk yang bertuliska “Je Suis Charlie”. Hari minggu kemarin, saat menonton siaran langsung Liga Italia yang menampilkan derby sepakbola terpanas di muka Bumi A.S ROMA melawan LAZIO. Saya menyaksikan LAZIO, klub favorit salah seorang teman saya, yang pernah diperkuat pemain legendaris Diego Simeone yang sekarang melatih Atletico Madrid ini mengganti logo sponsor di depan jersey pemainnya dengan tulisan “Je Suis Charlie”.
Di Perancis sendiri, aksi mengutuk terorisme terkait “Charlie Hebdo” Minggu (11/1/2015), tercatat sebagai aksi terbesar dalam sejarah Perancis. Tercatat setidaknya ada 3,7 juta orang yang turun ke jalan. Pengunjuk rasa terbanyak ada di Paris, dengan jumlah peserta yang mencapai 1,6 juta orang. Sementara aksi unjuk rasa di kota-kota lain diikuti puluhan hingga ratusan ribu peserta, antara lain di kota Nice, Toulouse, Pau, Nantes, Lyon, Marseille, Lille, dan Lyon.
Ini lebih besar dari peristiwa penyambutan Jenderal Charles de Gaulle seusai berakhirnya Perang Dunia II yang terjadi pada 26 Agustus 1944 yang kemudian mengantar Charles de Gaulle menjadi presiden ke-18. Ini juga melebihi pesta perayaan kemenangan Perancis atas Brazil yang mengantar mereka menjadi juara dunia di negeri sendiri.
Bukan hanya rakyat biasa yang ikut dalam unjuk rasa ini, bahkan pemimpin dunia pun tak mau ketinggalan hadir dalam aksi ini. Mulai dari Presiden Perancis Francois Hollande, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Ratu Rania Abdullah dari Jordania, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang atas kebijakannya pernah membunuh 17 Wartawan pun tak ketinggalan ikut serta.
Mereka semua ada di sana untuk menyampaikan satu suara « Kebebasan berekspresi dan bersuara harus dibela » .
Alice Blanc, seorang mahasiswa hukum di Paris, mengutip Voltaire yang menyebutkan “Saya tidak setuju dengan apa yang harus Anda katakan, tapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya.”
Nyaris seluruh dunia menyatakan hal yang sama. Je Suis Charlie, saya adalah Charlie!
Tapi nyaris, tentu tidak berarti semua. Satu suara kecil sayup-sayup terdengar dari benua Amerika. David Brooks, kolumis New York Times berani melawan arus opini dunia dengan mengatakan “I AM NOT CHARLIE”, Saya Bukan Charlie!
Brooks mengatakan ini bukan tanpa alasan. Dalam artikelnya yang dimuat di New York Times pada tanggal 8 Januari 2015 kemarin, http://www.nytimes.com/2015/01/09/opinion/david-brooks-i-am-not-charlie-hebdo.html?_r=1 Warga Amerika kelahiran Canada dan beragama Yahudi ini mengatakan :
“Hal pertama yang harus saya katakan, adalah bahwa apa pun yang mungkin telah anda pasang pada halaman Facebook Anda kemarin, saya kira tidaklah tepat ketika kebanyakan dari kita mengatakan, “Je Suis Charlie Hebdo”, atau “Saya Charlie Hebdo”. Sebab sebagian besar dari kita tidak benar-benar terlibat dalam jenis humor kasar yang sengaja menyinggung perasaan (sebagian kalangan) sebagaimana media itu mengkhususkan diri. Kebanyakan dari kita (masih) menunjukkan (paling tidak) sedikit rasa hormat kepada orang yang memiliki aliran dan kepercayaan yang berbeda. Kita berusaha untuk membuka percakapan dengan mendengar dibandingkan dengan melecehkan.”
Tidak perlu waktu lama, David Brooks pun segera panen hujatan pada kolom komentar di artikel yang dia tulis. Meskipun ada segelintir yang sependapat dengan pandangannya, tapi mayoritas 1393 komentar yang masuk dalam menanggapi artikel yang ditulisnya ini berisi hujatan. Ada yang mengatakan media Amerika pengecut, ada yang menyamakan penulis ini dengan masyarakat yang menyalahkan perempuan yang diperkosa karena si perempuan memakai rok mini. Ada yang menyebutnya naïf, karena David Brooks sendiri bisa seperti ini karena mendapat manfaat dari kebebasan berekspresi. Tapi justru anti kebebasan berekspresi.
Dalam keadaan normal, fenomena ini akan terlihat aneh. David Brooks, seorang Yahudi konservatif, pendukung pendudukan Irak yang berasal dari Amerika, negeri tempat filsafat pragmatisme berasal. Mampu melihat tragedi Charlie Hebdo ini dari sudut pandang berbeda.
Ajaibnya lagi, kejadian yang dia komentari ini ada di Perancis. Negeri tempat lahirnya filsafat Post Modernisme sebagai antitesis dari modernisme yang menyamaratakan nilai yang dianut semua orang.
Post Modernisme memandang tiap manusia itu unik dan berbeda, cara pandang terhadap nilai yang dianut juga. Dengan sudut pandang seperti ini, seharusnya Perancis bisa melihat, sensitifnya Umat Islam seperti mereka melihat sensitifnya Yahudi terhadap lambang swastika Nazi. Bukan karena Yesus simbol agama dan Muhammad juga simbol agama lalu keduanya diperlakukan sama dan merasa keduanya boleh dihina.
Kalau simbol-simbol Nazi bisa menjadi pengecualian bagi kebebasan berpendapat, lalu apa sulitnya mereka menerima fakta bahwa Muhammad juga adalah isu sensitif bagi sekelompok orang yang kebetulan bukan lahir sebagai Yahudi.
Bukankah dalam post modernisme, definisi Agama sendiri yang secara sepihak dibuat berdasarkan definisi barat juga digugat?
Berbicara soal agama ini betul, kita tidak menampik Perancis sekuler total, tapi ini kan soal ilmu sosial, bukan sains yang kaku. Dan kalau mau dibahas, soal simbol agama ini pun mereka sebenarnya bias.
John Bowen, antropolog dari University of Washington in Saint Louis penulis buku “Sumatran Politics and Poetics; Gayo History 1900 – 1989”, dalam karyanya yang berjudul “Why the French Don’t Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space” mengulas fakta bagaimana orang Perancis yang begitu mengagungkan LAICITE (Sekularisme) sangat sensitif dengan simbol Islam yang ditampilkan di ruang public seperti Jilbab. Tapi mereka bisa menerima jika orang berkalung salib di depan umum. Padahal keduanya merupakan simbol agama.
Jadi, siapapun yang masih memiliki hati nurani pasti menyesalkan peristiwa terorisme yang menyebabkan tewasnya 12 orang di Perancis ini. Cuma supaya tidak terus terulang, bukankah akar permasalahannya harus diselesaikan?.
Tapi dalam suasana kemarahan yang mendunia seperti sekarang. Nyaris tak ada lagi ruang untuk membahas permasalahan secara rasional. Setelah terjadinya peristiwa yang memilukan ini, alih-alih berubah untuk sedikit berempati. Melihat dukungan dunia yang sedemikian besar, Charlie Hebdo tanpa ragu menabuh genderang perang. Mereka menerbitkan edisi baru lagi dengan menggambarkan sesosok lelaki Arab (yang bisa saja dipersepsi sebagai Nabi Muhammad) memegang karton dengan tulisan “Je Suis Charlie”.
****
Benarlah apa yang dikatakan Sastrawan besar Pramoedya, zaman berubah manusia sama saja. Tidak peduli apakah dia seorang sekuler total atau agamis total,pada saat sedih dan marah manusia tak lagi terlihat bedanya.
Siapapun orang yang berani mengajak masyarakat berpikir rasional untuk kasus Charlie Hebdo, dalam skala dunia akan bernasib sama seperti orang yang tidak mengutuk Dosen Rosnida Sari di Aceh. Menuai hujatan, kutukan dan mendapat label. Jika dalam kasus Rosnida Sari, orang yang berani mengajak berpikir rasional seperti Fajran Zain yang menulis di Serambi Indonesia, mendapat label Anti Islam, Liberal sampai pembela kafir. Maka dalam skala jauh lebih besar orang yang berani mengajak masyarakat untuk berpikir rasional seperti David Brooks yang menulis di New York Times, segera mendapat label ANTI KEBEBASAN BEREKSPRESI.
*Pemerhati sosial budaya dan politik