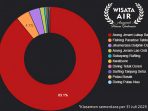Oleh Nab Bahany As
 Kebudayaan sering kali diartikan sebagai suatu kesenian dan ritual upacara tradisi, jarang diterjemahkan dalam bentuk universal yang berlaku dalam suatu ruang dan suatu waktu. Akibat penyempitan pengertian kebudayaan ini, maka berbicara politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya lainnya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kebudayaan.
Kebudayaan sering kali diartikan sebagai suatu kesenian dan ritual upacara tradisi, jarang diterjemahkan dalam bentuk universal yang berlaku dalam suatu ruang dan suatu waktu. Akibat penyempitan pengertian kebudayaan ini, maka berbicara politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya lainnya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kebudayaan.
Penafian kebudayaan yang terjadi selama puluhan dalam pembangunan bangsa kita telah menimbulkan berbagai gejolak sosial kemasyarakatan yang sulit dicari solusi penyelesaiannya, baik di tingkat lokal maupun secara nasional. Itu semua akibat dari tidak seimbangnya pembangunan kebudayaan dalam arti nilai-nilai dengan pembangunan fisik material yang kita rancang selama puluhan tahun di negeri ini.
Dampak dari ketidakseimbangan pembangunan kebudayaan dengan pembangunan fisik material, jelas sekali tergambar dalam buku: “Aceh, Antara Cinta dan Keangkuhan”, yang ditulis Baharuddin AR. Hampir semua gejolak dan persoalan sosial-kerakyatan yang terekam dalam buku ini adalah kerena tidak terbangunnya tatanilai budaya masyarakat secara totalitas. Perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada ekonomi yang sifatnya sangat kapitalistik, ternyata telah membuat bangsa ini gagal dalam menempatkan manusia sebagai manusia.
Dalam budaya “keanggkuhan” yang dimaksudkan dalam buku ini, manusia dihargai hanya karena kedudukan, karena pangkat dan jabatan. Bukan manusia sebagai manusia. Maka siapa yang berkuasa dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak-hak kemanusiaan dalam berbagai tindakan di luar cinta kasih antar sesama manusia itu sendiri.
Apa yang terjadi di Aceh dalam beberapa kurun terakhir, yang direkam sang penulis dalam buku ini, yang diistilahan dengan “keangkuhan” sebenarnya adalah bahasa lain yang ingin dikatakan penulis buku ini bahwa betapa telah “carut-marutnya” kondisi kehidupan sosial budaya kita dan sosial keagamaan yang tak lagi beretika dan berestetika, yang seolah-olah semua pelanggaran itu adalah hal yang sudah lumrah dalam menjalani aktifitas sehari-hari.
Tata nilai yang sebelumnya menjadi sanjungan dan kebanggaan lokal (orang Aceh) dalam mengatur sisi-sisi kehidupan yang harmoni, kemudian harus berhadapan dengan berbagai prahara budaya kekerasan, ketidakadilan, kesemena-menangan, kearogansian dan sejenisnya yang identik dengan pelangaran-pelanggaran norma, tatasusila kehidupan adat dan istiadat masyarakat yang sebelumnya telah terbukti bahwa tatanilai tersebut dapat memberikan kenyamanan dan keharmonisasian bagi kehidupan masyarakat penganutnya.
Makalah pengantar disampaikan pada diskusi bedah buku: “Aceh, Antara Cinta dan Keangkuhan” karya Baharuddin AR, di Rotya Café Banda Aceh, tanggal 23 Oktober 2013.
**Drs Nab Bahany As, Jurnalis, Ketua Lembaga Studi Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat (LSKPM) Aceh.
Itulah yang dimaksudkan dengan prahara budaya yang terjadi di Aceh, yang selalu bergolak dan bertarung antara cinta dan keangkuhan seperti yang digambarkan sang penulis dalam buku ini.
***
Buku setebal 284 halaman ini, memang menarik didiskusikan. Apalagi, buku ini secara kronologis mencoba mengangkat tiga demensi waktu dalam melihat persoalan sosial budaya keacehan, yaitu Aceh masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang (Aceh baru). Demensi historis yang terungkap dalam baku ini, meskipun agak melompat-lompat antara satu peristiwa dengan peritiwa lainnya, tidak berkolerasi dan berulang-ulang. Namun kita telah diberikan pemahaman perbandingan bagaimana memahami Aceh masa lalu, masa kini dan Aceh yang akan datang.
Dalam hal ini barang kali yang dapat dijadikan dalam mengungkapkan fakta sejarah dalam penulisan sebuah buku yang akan menjadi konsumsi umum tidak boleh difiksikan, direka-reka, tanpa meberikan sumber yang jelas. Sebab, bila suatu peristiwa sejarah itu salah diungkapkan dari peristiwa yang sesungguhnya, maka sejarah itu akan terus salah-fahami oleh siapa saja yang akan membacanya.
Oleh sebab itu, kematian Jenderal Kohler yang menurut buku ini dibunuh oleh seorang wanita biasa dengan sebilah pisau dapur di pekarangan Mesjid Raya Baiturraman (hal: 6), hendaknya dapat ditilik ulang sebagai kebenaran suatu peristiwa sejarah. Sebab, dalam banyak catatan, Kohler tewas di depan Mesjid Raya Baiturrahman karena tertembak oleh seorang pasukan Aceh yang menyelinap di sebatang pohon gelumpang. Karenanya, monument tempat tewasnya Jenderal Kohler di depan Mesjid Raya sekarang sengaja ditanam kembali sebatang pohon gelumpang sebagai bukti sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam melawan tentara Belanda ketika itu.
Buku yang dilengkapi dengan lampiran sepuluh judul puisi ini juga memberikan keterangan, bahwa ada luka yang mendalam dari pengalaman sang penulis terhadap Aceh, akibat betapa telah sirnanya kasih sayang diantara sesama ketika cinta berubah jadi keangkuhan. Maka:
“Yang tersisa
hanyalah singga-singa buas dalam kehausan
baju-baju loreng berwajah bara
lalu batinku berteriak dalam amarah kelelahan … …”. (hal. 272).
Prahara keangkuhan lain yang maha dahsyat telah mempengaruhi kebudayaan Aceh, dan bahkan hampir semua kearifan lokan diseluruh tanah air, menurut buku ini adalah, adalah pengaruh UU. Nomor: 5/1979, yang nmenyeragamkan Pemerintahan Desa semasa Orde Baru. Dengan Undang-Undang ini Aceh harus rela kehilangan fungsi lembaga-lembaga budaya dalam mengatur kehidupan tatanan masyarakat sehari-hari (hal. 171). Sebagai akibat dari prahara keangkuhan kebudayaan ini harus menanggung berbagai persoalan sosial baru, mulai dari hal-hal yang terkecil hingga dalam bentuk skala nasional, dan bahkan secara global.
***
Secara keseluruhan, buku yang mengangkat beragam persoalan Aceh dalam bentuk pengalaman yang diperkaya dengan referensi oleh sang penulis, tentu saja memiki plus-minus ketika kita mencoba mengapresiasiakannya. Sebagai sebuah buku kumpulan tulisan, sudah tentu persoalan keacehan yang diangkat dalam buku ini tidak membarikan penyelesaiannya secara tuntas. Sang penulis hanya memberikan informasi mengenai peritiwa demi peristiwa yang pernah terjadi dan melanda Aceh.
Bahkan sesekali kita juga menemukan pengunkapan fakta-fakta sejarah dalam merelefansikan Aceh masa lalau dan masa kini yang tersaji dalam buku ini terkesan tidak memiliki dasar yang memadai. Secara tioritis akademik, penulisan sejarah tanpa dasar yang jelas mungkin perlu dipertanyakan sebagai pertanggungjawaban keilmiahan.
Di sisi lain, secara metedelogis saya hampir tidak bisa menjelaskan buku: “Aceh, Antara Cinta dan Keangkuhan” ini harus dikelompokkan dalam apa. Apakah dalam bentuk novel, esais, atau sebuah buku ilmiah popular akademik. Yang jelas, apapun bentuknya, buku ini adalah sebuah karya nyata hasil proses berfikir yang perlu disambut dan perlu dibaca untuk memahami Aceh dalam bentuk historis dan Aceh dalam bentuk kontemporer sekarang ini.aceharts.com.
*Nab Bahany As, adalah budayawan Aceh tinggal di Banda Aceh.