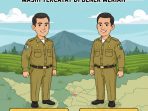Oleh : Dr. Johansyah, MA*
 Merupakan petaka pendidikan ketika kasus tindak kekerasan di sekolah masih terus terjadi. Kasus baru yang menjadi sorotan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru di Bandar lampung terhadap para muridnya satu kelas hanya karena salah menjawab soal ulangan. Walau tidak dapat dipercaya sepenuhnya, menurut para orangtua murid, anak-anak mereka sering mendapat perlakuan yang tidak pantas dari guru tersebut.
Merupakan petaka pendidikan ketika kasus tindak kekerasan di sekolah masih terus terjadi. Kasus baru yang menjadi sorotan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru di Bandar lampung terhadap para muridnya satu kelas hanya karena salah menjawab soal ulangan. Walau tidak dapat dipercaya sepenuhnya, menurut para orangtua murid, anak-anak mereka sering mendapat perlakuan yang tidak pantas dari guru tersebut.
Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi di dunia sekolah kita, di mana guru melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya dengan beragam motif. Dengan tidak bermaksud untuk menghakimi siapa yang salah, saya akan coba menguraikan kemungkinan penyebab terjadinya kekerasan di sekolah, dan upaya untuk membenahinya sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik.
Pertama, kekerasan dikarenakan tidak adanya tata tertib sekolah yang jelas tentang tindakan terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Hal ini membuat guru menerapkan pola punishment (hukuman) sesuka hatinya, bukan berdasarkan ketetapan sekolah sebagai konsensus bersama. Untuk itu, sekolah seharusnya membuat tata tertib baku yang disepakati tentang apa jenis hukuman serta bagaimana menerapkannya sanksi terhadap murid yang melanggar aturan sekolah. Hukuman tersebut tentu harus berdasarkan nilai-nilai manusiawi dan bebas dari unsur kekerasan. Aturan tersebut bukan saja disepakati antar guru di sekolah, tetapi juga antara sekolah dengan orangtua murid.
Kedua, penyebab lain terjadinya kekerasan di sekolah karena supervisi dan kepemimpinan sekolah yang sangat lemah. Sejatinya pimpinan sekolah harus mengetahui setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru dan stafnya, apalagi menyangkut dengan pola penerapan hukuman yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Kembali pada persoalan pertama tadi, bahwa harus ada aturan tertulis yang disepakati antara pimpinan sekolah dan guru.
Ketiga, penyebab tindak kekerasan di sekolah adalah karena sang guru tidak memahami psikologi pendidikan dengan baik. Sebab mendidik anak pada intinya harus didasarkan pada upaya memahami kondisi kejiwaan anak. Anak memiliki karakteristik dan watak yang berbeda, latar belakang keluarga berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, dan bakat minat yang berbeda pula. Oleh sebab itu, perlakuan kepada masing-masing mereka tentunya juga berbeda. Pemahaman terhadap kondisi setiap anak akan sangat bermanfaat bagi guru terutama ketika dia berusaha melakukan pendekatan terhadap murid-muridnya.
Jika guru memiliki kematangan psikologis dalam mendidik, saya yakin tidak ada masalah yang berarti baginya, sebab guru seperti ini biasanya memiliki beragam strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jika dia gagal dengan satu metode, maka dia akan menempuh dan mencoba metode lain. Begitu seterusnya sampai dia menemukan cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Sebaliknya, guru yang suka marah dan tidak suka dikritik, itu tandanya dia miskin metode dan minim penguasaan materi.
Terkait dengan pentingnya penguasaan psikologi pendidikan oleh guru, hal ini sejatinya menjadi masalah sentral yang disorot oleh fakultas-fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin kurikulum untuk calon guru perlu dibedah dan dievaluasi lagi, di mana kekurangan yang perlu dibenahi. Demikian halnya pemerintah yang juga perlu mengevaluasi mekanisme rekrutmen calon guru. Selama ini belum ada sistem rekrutmen guru yang berorientasi pada profesionalisme seorang pendidik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya uji kelayakan guru dari aspek psikologisnya secara intens. Calon guru hanya disuguhkan soal-soal teoritis tentang pengetahuan umum, pengetahuan agama, dan beberapa pengetahuan lainnya. Padahal itu semua tidak berkaitan dengan bidang yang digeluti oleh calon guru, dan tidak dapat mengukur kematangan psikologisnya.
Keempat, tindak kekerasan yang terjadi di sekolah disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara sekolah dengan keluarga. Orangtua tidak pernah menanyakan kesulitan apa yang dihadapi anaknya di sekolah kepada guru, dan guru juga tidak pernah memberi informasi tentang perkembangan anaknya di sekolah. Setiap murid yang membuat masalah di sekolah tidak serta merta dikomunikasikan dengan orangtua. Orangtua juga demikian, malah ada yang tidak mau tau dengan permasalahan anaknya di sekolah.
Dalam pendidikan komunikasi adalah keharusan. Komunikasi pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pendidikan kolektif yang tidak hanya dipikul sepihak oleh sekolah maupun orangtua semata. Komunikasi pendidikan juga menghindari persoalan berlarut-larut terkait murid yang membuat pelanggaran di sekolah. Kelancaran komunikasi antara sekolah dengan orangtua juga sebenarnya menjadikan anak merasa terus diawasai secara bersama sehingga dia lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pelanggaran.
Kerenggangan komunikasi antara sekolah dengan orangtua sebenarnya bisa menjadi pemicu kesalahpahaman antara keduanya. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di sekolah selama ini ternyata memang demikian, di mana orangtua salah paham dengan pihak sekolah ketika guru memberikan sanksi kepada anaknya, padahal anaknya sudah berulang kali melakukan pelanggaran. Akibat kurangnya komunikasi, maka terjadilah kesalahpahaman dan saling menyalahkan.
Saat penelitian di beberapa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Banda Aceh dan Aceh Besar, saya melihat di antara kelebihan SDIT ini adalah bahwa sekolah memiliki komunikasi yang sangat baik dengan keluarga. Sekolah menyediakan buku pemantau dan komunikasi bagi setiap siswa. Dalam buku tersebut orangtua melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh anaknya di rumah serta bagaimana perkembangannya. Demikian juga sekolah, selalu memberikan laporan rutin kepada orangtua tentang bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Sepertinya model komunikasi ini perlu ditiru oleh sekolah-sekolah lain dalam upaya memaksimalkan kerja sama antar sekolah dan keluarga.
Sebagai catatan akhir, saya juga perlu mengingatkan para orangtua agar bersikap tabayyun (klarifikasi, mencari kebenaran) terhadap beragam informasi yang diberikan oleh anak. Biasanya anak yang melakukan kesalahan di sekolah memanipulasi informasi. Mereka menyembunyikan fakta sebenarnya dan menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi. Intinya setiap informasi yang diterima harus dikomunikasikan dan disaring lagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sebaiknya juga tidak semua sanksi yang diberikan oleh guru dengan serta merta diterjemahkan sebagai tindak kekerasan dan harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini, berulang kali saya menegaskkan dalam beberapa tulisan bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di dunia pendidikan perlu pengkajian ulang. Dampak positif UU ini jelas ada, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan. Amin.
*Johansyah adalah Pemerhati Pendidikan, Tinggal di Bener Meriah. Email; johan.arka@yahoo.co.id.