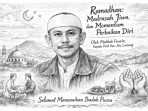Jakarta-LintasGayo.co : Orang Gayo mulai tidak menuturkan, tidak mengajarkan, dan mulai tidak mempelajari bahasa Gayo. “Fenomena ini makin terlihat dari generasi kelahiran 1970 sampai sekarang. Sementara, generasi kelahiran 1930-1960-an sudah mulai berkurang. Fenomena ini terjadi pula pada bahasa lokal lainnya di Aceh dan di Indonesia,” kata linguis sekaligus peneliti, Yusradi Usman al-Gayoni saat diminta paparannya terkait kondisi kekinian bahasa Gayo dalam Focus Group Discussion (FGD) Prakongres Peradabadan Aceh yang dihadiri Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, penutur masing-masing bahasa lokal di Aceh, inisiator acara, akademisi, peneliti, sastrawan, sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten/kota dari Aceh sejumlah 50 peserta di Hotel Aryaduta Jakarta, Jum’at (26/6/2015).
Dalam sejumlah ranah baik formal maupun ranah informal, ungkapnya, orang Gayo terutama yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi satu sama lain. “Termasuk, dalam ranah keluarga dan lingkungan ketetanggaan. Lingkungan (ekologi) bahasa di Gayo sudah berubah. Otomatis, generasi tua juga menyesuaikan, berbahasa Indonesia,” katanya.
Dijelaskan anggota tim peneliti Peran Bahasa dan Kebudayaan dalam Konteks NKRI: Keanekaragaman untuk Persatuan dan Kesatuan di Aceh Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, ada dua faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. “Dari sisi mikro atau internal, kesadaran penggunaan, pembelajaran, dan pengajaran bahasa Gayo memang rendah. Ini kembali ke orang Gayo sendiri. Selama orang Gayo menggunakan bahasa Gayo, maka bahasa Gayo akan tetap ada (lestari). Sebaliknya, kalau orang Gayo sudah tidak berbahasa Gayo, maka potensi keterancaman kepunahan bahasa ini untuk jangka panjang semakin besar. Belum lagi, bermigrasinya orang Gayo keluar Gayo. Ini juga turut memengaruhi,” tegasnya.
Dari penutur bahasa lokal yang lebih besar, sambunnya, bahkan di atas satu juta pun, tidak ada jaminan. “Bahasa Aceh, Melayu, Jawa, Bugis, dan beberapa bahasa lokal lainnya yang penuturnya di atas satu juta, tidak ada jaminan akan tetap selamat, bila penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tadi,” sebutnya.
Faktor kedua, jelasnya, menyangkut kondisi makro atau eksternal, yaitu adanya keberagaman bahasa, budaya serta etnik di Gayo, perkawinan silang, pendidikan, informasi dan teknologi, media, dan politik. Apalagi, orang Gayo memang sifatnya terbuka, toleran, dan akomodatif terhadap pendatang/perubahan. Dengan demikian, sambunnya, perlu dikuatkan kesadaran dari orang Gayo sendiri terkait keterwarisan bahasa Gayo. “Kesadaran ini yang perlu ditingkatkan, selain terus memperkuat riset dan dokumentasi tertulis. Akibatnya, alih kegayoan terjadi baik secara lisan maupun secara tertulis. Juga, dengan membuat Qanun Bahasa Gayo dan menjadikan bahasa Gayo sebagai materi muatan lokal di daerah Gayo,” katanya.
Zonasi Muatan Lokal
Soal pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di Aceh, dijelaskan Staf Ahli/Asisten Anggota DPD/MPR RI Propinsi Aceh di Senayan (2009-2019) tersebut, meski diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dalam Bab XXXI pasal 221 ayat (4) yang berbunyi “Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal,” dan ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun, namun perlu dibuat zonasi. “Bahasa Aceh tetap dikenalkan di seluruh daerah kabupaten/kota di Aceh, supaya masyarakat Aceh mengetahui kekayaan bahasa dan menghargai perbedaan. Tapi, pelaksanaan mulok bahasa Aceh khusus di daerah pesisir Aceh. Bahasa Gayo juga demikian, tetap dikenalkan di seluruh Aceh. Namun, pelaksanaannya khusus di daerah Gayo (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Bener Meriah). Bahasa-bahasa lokalnya lainnya juga seperti itu. Kalau tidak dizonasikan, khawatir terjadi Acehnisasi. Tentu, ini tidak kita harapkan. Malah, malah dapat menghilangkan bahasa lokal/suku lainnya di Aceh,” tegas Yusradi, sambil menambahkan, persoalan Acehnisasi ini yang membuat simbol, bendera, dan Wali Nanggroe makin ditolak di Gayo.
Dialek Bahasa Gayo
Dalam kesempatan itu, Yusradi juga menerangkan dialek bahasa Gayo dan jumlah orang Gayo yang berjumlah 500 ribu jiwa. “Ada beberapa dialek bahasa Gayo. Dialek Gayo Lut dipakai di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Gayo Deret di daerah Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lokop Serbejadi di Kabupaten Aceh Timur, Gayo Kalul di Aceh Tamiang, Gayo Blang atau Gayo Lues di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara,” akunya.
Dalam persebarannya, selain mendiami daerah Gayo, mereka menyebar ke daerah pesisir Aceh, pelbagai daerah di Indonesia, dan sampai ke luar negeri. “Daerah Sibayak Lingga Sumatera Utara itu juga keturunan orang Gayo. Bahkan, mereka mengaku orang Gayo bersuku Gayo,” sebutnya, sambil menambahkan, waktu pisah bahasa Gayo dengan bahasa Karo 2298 tahun, dan bahasa Gayo dengan bahasa Alas sekitar 1745 tahun.
Yusradi juga mengungkapkan temuan Balai Arkeologi Medan yang menyebutkan bahwa orang Gayo sudah mendiami Aceh (Loyang Mendale dan Loyang Ujung Karang di Gayo, Takengon) sejak 7000 tahun yang lalu. “Temuan ini merekonstruksi ulang sebaran manusia prasejarah di Indonesia. Sebaran di Pulau Sumatera tidak kemungkinan dimulai dari Gayo, Aceh. Bahkan, temuan para Arkeolog tersebut makin menguatkan bahwa bahasa Gayo ikut memengaruhi bahasa-bahasa Austronesia,” katanya.
Tak lupa, Yusradi kemudian memberikan beberapa buku yang ditulisnya—Tutur Gayo Edisi I, Tutur Gayo Edisi II, Tutur Gayo Lues, dan Ekolinguistik yang merupakan buku Ekolinguistik pertama di Indonesia—kepada Ketua Panitia Kongres Peradaban Aceh Dr. Ahmad Farhan Hamid dan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar. (AF)