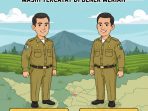(Superioritas dan Infrioritas Bahasa Etnik Terhadap Bahasa Urban)
Oleh: Hasan Basri, S.Ag
 BAHASA Gayo (pengucapan: Gayô) adalah suatu bahasa dari rumpun Austronesia yang dituturkan oleh suku Gayo di provinsi Aceh, yang terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Lokop Serbe Jadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bahasa Gayo merupakan bahasa yang dituturkan oleh etnis minoritas yang terkadang mengalami fenomena infrioritas di tengah komunitasnya sendiri. Infrioritas yang muncul akibat “suprioritas” bahasa urban yang yang dituturkan oleh mayoritas etnik lainnya. Pra terjadinya akulturasi dan difusi kebudayaan terutama kebudayaan yang dibawa penjajah (Belanda dan Jepang) bahasa gayo merupakan satu-satunya bahasa etnik yang digunakan sebagai bahasa komunikasi antara sesama urang (etnis) gayo. Sebagai bahasa agama, bahasa Arab telah mendapatkan “ruang” di bumi Gayo, dan tanpa infrioritas etnis Gayo merasa berkewajiban untuk mempelajarinya.
BAHASA Gayo (pengucapan: Gayô) adalah suatu bahasa dari rumpun Austronesia yang dituturkan oleh suku Gayo di provinsi Aceh, yang terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Lokop Serbe Jadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bahasa Gayo merupakan bahasa yang dituturkan oleh etnis minoritas yang terkadang mengalami fenomena infrioritas di tengah komunitasnya sendiri. Infrioritas yang muncul akibat “suprioritas” bahasa urban yang yang dituturkan oleh mayoritas etnik lainnya. Pra terjadinya akulturasi dan difusi kebudayaan terutama kebudayaan yang dibawa penjajah (Belanda dan Jepang) bahasa gayo merupakan satu-satunya bahasa etnik yang digunakan sebagai bahasa komunikasi antara sesama urang (etnis) gayo. Sebagai bahasa agama, bahasa Arab telah mendapatkan “ruang” di bumi Gayo, dan tanpa infrioritas etnis Gayo merasa berkewajiban untuk mempelajarinya.
Hipotesis bahasa Arab sebagai salah satu bahasa urban yang dianggap “paling awal” mendatangi Gayo tentu dapat diterima. Gayo yang dijadikan target bagi ekspansi dakwah para penyebar Islam memungkinkan terjadinya akulturasi dan difusi kebudayaan antara kelompok urban dengan etnis Gayo sebagai peribumi. Bahasa Arab sebagai bahasa urban yang hadir dengan “kemasan” dan “wajah” Islam, dengan cepat diterima kehadirannya oleh etnis Gayo. Superioritas bahasa Arab tidak menjadikan bahasa gayo sebagai bahasa infrioritas, tereliminasi dan terpinggirkan, tetapi justru menjadikan khazanah bahasa Gayo sebagai bahasa yang kaya akan kata serta makna.
Gayoisasi budaya Arab (tulisan dan bahasa) memudahkan etnis gayo mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa “wajib” dalam beragama, walaupun demikian urang gayo masih tetap mempertahankan bahasa gayo sebagai bahasa ibu yang resmi digunakan sebagai bahasa komunikasi dan interaksi sosial. Bahasa Arab telah menampati “ruang” tertentu di Gayo, “ruang” istimewa yang husus disediakan urang gayo serta memungkinkannya “bersanding” penuh kemesraan dengan bahasa gayo sebagai bahasa peribumi.
Kehadiran “bahasa urban” tidak diharapkan “menggeser posisi” bahasa gayo sebagai bahasa peribumi, menjadikannya sebagai bagian dari sejarah semata, menempatkannya pada sangkar nostalgia yang dikemas dalam kemasan idealitas semata. Bahasa Gayo merupakan bagian warisan budaya dari leluhur yang harus dilestarikan. Keengganan untuk melestarikannya, ketidak perdulian atas kepunahannya tentu tidak diharapkan, karena bahasa Gayo adalah eksistensi dan karakterisrik dari etnis Gayo.
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Abdul Rachman Patji mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa etnis seperti urbanisasi dan perkawinan antar etnis. Selain itu, faktor lain yang juga memicu kepunahan bahasa antara lain para penutur berpikir dirinya inferior secara sosial, terikat masa lalu, sisi tradisional dan kehidupan ekonomi yang stagnan.
Dibawah ini dideskripsikan beberapa contoh dialog komunitas masyarakat sebagai penutur bahasa etnis, hususnya di bumi Gayo:
Jangan nangis nak ibu lagi masak sayur ni, sebentar lagi ayahmu pulang dari kebun pasti ayahmu lapar dan capek nak. Jangan nangis nak ya…..jangan nangis nak ya…….ilustrasi dialog ini terjadi antara seorang ibu dengan anaknya di salah satu pedesaan di Gayo.
Ibu …..banyak sekali PR yang harus kami kerjakan di rumah, jangan lagi ibu tambah dengan PR baru bu…..tolong bu, kalau setiap hari kami harus menyelesaikan PR di rumah kapan lagi waktu kami untuk bermain dengan teman-teman bu? Ibu tidak bermaksud menambah PR baru nak, tapi mata pelajaran ini sangat penting, jadi kalian harus mengerjakan tugas yang ibu berikan ini, agar kalian tidak kesulitan nanti ketika mengahadapi ujian ahir. Dialog ini terjadi antara siswa-siswi dengan gurunya pada salah satu sekolah di Gayo.
Surga akan merindukan orang-orang yang berbuat dan beramal di dunia, sebaliknya neraka juga merindukan orang-orang yang bermala jahat di dunia. Hadirin hadirat siding jama’ah jum’at yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah menyediakan dua tempat untuk kita di hari akhirat kelak, pertama syurga dan kedua neraka. Kedua tempat ini merupakan pilihan bagi kita, dan sangta tergantung dari amal dan perbuatan kita ketika di dunia…..Ilustrasi: khutbah Jum’at yang presentasikan oleh khatib di salah satu Masjid di Celala.
Becak….! Becak…..! Becak…..! teriak seorang ibu. Kemana bu? Tanya abang becak. Tolong antarkan saya ke Kebayakan dik, berapa ongkosnya dik? Biasanya dari sini ke Kebayakan ongkosnya Rp. 5000 (lima ribu rupiah)…O…ya..ini ongkosnya dik….terima kasih bu….dialog ini terjadi antara abang becak dengan seorang ibu di pusat perbelanjaan di Gayo.
Berapa sekilo tomatnya bu? Kalau yang ini dua ribu satu kilo, sedangkan yang ini seribu lima ratus. Saya tiga kilo bu…..berapa bu….tiga kilo enam ribu…terima kasih bu… ya… sama-sama. Dialog antara seorang ibu dengan penjual sayur-syuran di Gayo.
Ilustrasi dialogis diatas terjadi antara sesama etnis Gayo. Ilustrasi tersebut mendeskripsikan mereka sebagai penutur dan pemiliki bahasa ibu yang inferior secara sosial, komunitas etnis yang “enggan” dan “minder” menuturkan bahasa gayo sebagai bahasa komunikasi dan interaksi sosial mereka. Perilaku tersebut telah menelantarkan serta menjadikan bahasa etnis sebagai bahasa yang infiroritas di tengah-tengah ekosistem dan komunitasnya. Inferioritas yang berujung pada marginalisasi bahasa gayo di tengah komunitasnya, justru menjadi penyebab lahirnya sisnisme dan “sindiran” dari komunitas penutur bahasa urban terhadap bahasa gayo.
Marginalitas bahasa gayo diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi bahasa gayo yang berada pada posisi marginal atau berada pada konteks “pinggiran” di pusaran komunitas etnis yang seharusnya menuturkan bahasa gayo sebagai bahasa kesehariannnya. Kurangnya afirmasi pemerintah serta etnis penutur terhadap ketersediaan ruang bagi penuturan bahasa Gayo, menjadikan bahasa gayo sebagai bahasa yang “termaginalkan” dan menjadi tamu yang sangat asing di rumahnya sendiri, menjadi bahasa yang tidak diperhitungkan eksisitensinya di bumi Gayo.
Komitmen dari etnis gayo untuk menuturkan bahasa gayo merupakan keharusan dan keniscayaan. Komitmen ini akan menjadikan bahasa gayo tetap eksis dan menjadi “superioritas” di bumi Gayo, menjadikannya pantas dan layak dipelajari oleh “etnis urban” yang mendatangi Gayo. Bahasa gayo sebagai bahasa yang “dipelajari”, dapat disandingkan dengan bahasa “urban” yang semakin membanjiri daerah gayo. Kendatipun “bahasa urban” dianggap sebagai “tamu”, juga diberikan ruang tersendiri oleh atnis Gayo untuk menunjukkan “eksistensi” dirinya.
Lingkungan keluarga (etnis gayo) sebagai lingkungan pertama seorang calon penutur bahasa (anak) mengenal dan menuturkan bahasa gayo, diharapkan keseriusannya untuk menuturkan bahasa gayo sebagai bahasa komunikasi dan interaksi antara seluruh elemen anggota keluarga. Keluarga etnis gayo diharapkan sebagai benteng terahir yang berkomitmen serta berupaya untuk senantiasa menuturkan dan mempertahankan bahasa gayo sebagai bahasa ibu mereka. Kontinuitas penuturan bahasa etnik dalam lingkungan keluarga akan melahirkan sikap generasi etnik yang tidak “canggung”, tidak “minder” dan penuh peracaya diri tampil dengan tuturan bahasa etnik sebagai bagian dari jati diri etnik mereka.
Disamping itu lingkungan sekolah diharapkan memberikan “ruang” bagi siswa dan siswi etnis sebagai penutur, yang menggunakan bahasa Gayo sebagai bahasa komunikasi dan interaksi antara sesamanya. Guru sebagai orang yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah diharapkan “toleransi” terhadap siswa-siswi etnis penutur bahasa gayo. Wallahu a’lam bish shawab.
*Pemerhati sosial dan budaya Gayo