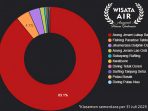(Antara Islam dan Akulturasi serta Difusi Kebudayaan)
ISLAM sangat menghormati dan memuliakan kaum perempuan, penghormatan yang diberikan Islam berlaku untuk seluruh kaum perempuan. Perempuan Gayo sebagai bagian dari kaum perempuan tentu layak menerima penghormatan ini.
Sabda Rasulullah SAW “syurga itu berada di bawah telapak kaki ibumu” merupakan indikasi dari pemuliaan dan pengangkatan harkat serta martabat perempuan. Islam tidak mengharuskan perempuan untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah kewajiban suami (laki-laki), namun tidak dapat dibantah hampir sebagian besar perempuan Gayo bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
Islam menjadikan sosok seorang ibu (perempuan) sebagai individu yang paling layak dihormati, dipergauli dengan baik, dimuliakan, namun terkadang hal ini “sulit” dirasakan oleh sebagian perempuan Gayo.
Sejarah membuktikan di tengah-tengah penghinaan dan penistaan terhadap kaum perempuan oleh budaya dan tradisi, justru Islam hadir dengan salah satu misinya memuliakan dan menghormati perempuan. Kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Islam pada perempuan tidak sebanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh kebudayaan dan peradaban manapun di dunia ini.
Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku bajik kepadanya?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “Ayahmu.” (HR. Bukhari)
Islam menjaga perempuan yang berharga ini dengan seperangkat aturan yang terkait dengan pola relasi individu antara pria dan wanita, perlakuan keluarga, serta perlakuan masyarakat dan Negara.
Kalimat yang ditulis oleh Atik Latifah dalam Suara Islam Online berhubungan dengan peringatan hari perempuan internasional yang digelar pada tanggal 08 Maret setiap tahunnya patut menjadi bahan renungan kita bersama, “Hari Perempuan Internasional hanyalah ajang ceremonial belaka, tidak memberikan efek bagi kehormatan perempuan yang sepatutnya dilindungi. Daripada hanya sekadar perayaan, hari perempuan sedunia seharusnya mengalihkan perhatian dunia pada tidak kredibelnya demokrasi sekular dalam menjaga kehormatan, kemuliaan dan hak dasar perempuan. Hanya Islam lah yang mampu menjaganya”.
Di kalangan masyarakat Gayo terdapat suatu adagium “edet kin peger ni agama” walaupun pengakuan terhadap kebenaran dari adagium ini masih membutuhkan penelusuran dan penelitian yang komprehensif terhadap sejarah panjang adat isti’adat serta budaya Gayo. Namun esensi dari adagium ini dapat dimaknai bahwa budaya, tradisi, adat isti’adat Gayo diterima oleh Islam, pelaksanaan adat isti’adat dalam keseharian masyarakat Gayo dapat diartikan dengan pemeliharaan terhadap ajaran agama.
Seiring dengan pesatnya perkembangan sosial di kalangan masyarakat, ditambah dengan karakteristik budaya Gayo yang dapat menerima kehadiran budaya lain, tentu akulturasi budaya, serta difusi budaya sulit untuk dihindari.
Sayangnya akulturasi[1] serta difusi kebudayaan[2] yang ditandai dengan meningkatnya heterogenitas, serta modernitas di tengah-tengah komunitas perempuan Gayo, bukan menjadikannya sebagai sosok perempuan yang teguh memegang budaya dan tradisinya sendiri, tapi justru menjadikan mereka sebagai pribadi atau individu yang tereleminasi dari budayanya, hilangnya kepercayaan diri dari mereka untuk tampil dalam masyarakat dengan budaya yang mereka miliki, munculnya sikap apatis terhadap perilaku menyimpang dari budaya Gayo yang semakin marak di kalangan masyarakat Gayo akhir-akhir ini, tentu semakin memuluskan jalan untuk kehancuran dan kepunahan budaya Gayo.
Seharusnya akulturasi dan difusi kebudayaan dimaknai sebagai hal positif kaitannya dengan penambahan serta memperkaya budaya Gayo dengan unsur dan nilai baru tanpa mengkerdilkan dan melemahkan budaya Gayo itu sendiri.
Karakteristik budaya Gayo yang “terbuka” dan lebih ramah terhadap budaya luar memungkinkan terjadinya akulturasi dan difusi kebudayaan secara cepat di kalangan perempuan Gayo. Difusi kebudayaan ini bahkan telah merasuki hampir keseluruh aspek kehidupan mereka, (pola kehidupan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik, sebagai politikus, sebagai pemimpin suatu instansi dan organisasi masyarakat).
Akibatnya jati diri, karakteristik, serta perilaku perempuan Gayo hampir tidak “dikenali” dalam masyarakat, ditambah dengan sikap mereka yang secara perlahan-lahan mulai meninggalkan budayanya sendiri, dan lebih “percaya diri’ tampil dalam interaksi sosialnya dengan budaya dan kultur lain.
Istilah sumang si opat sebagai warisan budaya Gayo yang seharusnya dipertahankan, (sumang pelangkahen, sumang penengonen, sumang pengunulen serta sumang perceraken) merupakan warisan budaya Gayo yang dilaksanakan secara turun temurun.
Namun sangat menyedihkan budaya sumang ini telah memudar bahkan hampir tidak diamalkan lagi di kalangan perempuan Gayo, hal ini ditandai dengan perilaku perempuan Gayo yang tidak mencerminkan budaya sumang siopat. Bahasa Gayo sebagai identitas dari eksistensi “perempuan Gayo” sudah jarang digunakan sebagai alat komunikasi, dikahwatirkan lambat laun bahasa Gayo akan hilang dan mengalami kepunahan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan Gayo yang mayoritas hidup di Dataran tinggi Gayo, tidak hanya berhubungan dengan lingkungan alam sekitarnya (Danau Lut Tawar, areal sawah dan perkebunan yang membentang luas, hutan, pegunungan, sungai yang mengalir, air pancuran, kabut pagi yang dingin), terlepas dari semua hal tersebut perempuan Gayo tentu tidak mungkin menghindar dari interaksi dengan masyarakat sekitarnya.
Pola interaksi sosial dengan masyarakat inilah yang mengharuskannya mempelajari, meniru serta beradaptasi dengan nilai-nilai sosial, pola kehidupan (budaya) dari masyarakatnya yang tidak tertutup kemungkinan telah bersentuhan dengan pola kehidupan modern yang cenderung individualistis dan materialistis serta konsumtif.
Pola kehidupan modern ini tanpa disadari telah berperan dalam menggiring perempuan Gayo untuk mendekonstruksi bangunan budayanya sendiri, mendistorsi budayanya dengan budaya lain, memiskinkan warisan budayanya yang sangat kaya. Pola kehidupan modern yang telah diakomodir perempuan Gayo telah menyebabkan terjadinya peningkatan budaya kerja di kalangan mereka.
Budaya kerja yang semakin meningkat akibat dari tuntutan kehidupan perempuan Gayo yang semakin kompleks, dan karena terjadinya difusi kebudayaan, juga berimbas pada tatanan perempuan Gayo, memaksa mereka cenderung hanya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, meniti dan mementingkan karir, mencari nafkah membantu suami.
Akibatnya perhatian dan pelayanan terhadap keluarga, terutama pelayanan pendidikan dan “kasih sayang” terhadap anak-anak justru menjadi kurang bahkan mungkin terabaikan.
Perempuan Gayo saat ini banyak yang bekerja tanpa memperhatikan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri yang harus mengurus rumah tangganya. Ibu yang seharusnya mencetak generasi penerus Gayo yang berkualitas, tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena aturan dalam dunia kerja sistem kapitalisme.
Bagaimana mungkin seorang perempuan dapat mengurus anak dan rumah tangganya jika jam kerja yang harus dilaksanakannya adalah seharian penuh. Hal ini mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.
[1]Koentjaraningrat: akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok dengan suatu kebudayaannya dihadapkan pada unsure-unsur asing yang secara perlahan-lahan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan sendiri.
[2]Suatu proses penyebaran unsure-unsur sosial budaya dari suatu kelompok ke kelompok masyarakat yang lain.
*Kepala KUA Kec. Celala Kabupaten Aceh Tengah